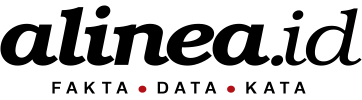No buy challenge 2025: Upaya adaptasi dan ancaman ekonomi nasional
No buy challenge 2025 atau tantangan tidak berbelanja menggema di media sosial dan menjadi viral. Fenomena ini menjadi tren di kalangan generasi atau gen Z dan kelompok masyarakat lainnya sebagai bentuk strategi berhemat dan melawan konsumerisme.
Pada dasarnya, tantangan ini mengajak individu untuk tidak membeli barang-barang di luar kebutuhan utama dalam jangka waktu tertentu. Meski tampak sebagai kebiasaan yang positif, fenomena memberikan konsekuensi yang lebih luas terhadap perekonomian, baik di tingkat individu maupun makroekonomi.
Gaya hidup atau dipaksa oleh keadaan?
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad mengatakan tren no buy challenge dapat dikaitkan dengan gaya hidup frugal living yang semakin diminati. Sebagian masyarakat, khususnya gen Z, mulai menerapkan pola hidup hemat—bahkan hingga ke tahap subsistensi ketat—guna mengalokasikan lebih banyak dana untuk tabungan atau kebutuhan yang lebih produktif.
Namun, di balik tren ini, ada realitas ekonomi yang lebih kompleks. Dalam konteks makro, disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Proporsi disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat hanya sekitar 75%, yang berkontribusi pada semakin menipisnya jumlah tabungan di tingkat rumah tangga. Dengan kata lain, keputusan masyarakat untuk menghemat bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup, melainkan juga reaksi terhadap tekanan ekonomi yang semakin berat.
Beberapa faktor struktural yang membebani daya beli masyarakat yakni meningkatnya biaya hidup dan beban kewajiban finansial, seperti premi asuransi wajib dan kenaikan pajak kendaraan pada 2025. Pengeluaran ini bersifat mandatori dan sulit dihindari, sehingga banyak orang terpaksa mengurangi pengeluaran lain, termasuk belanja barang konsumtif.
“Jadi kalau dilihat lagi upaya untuk melakukan no buy challenge atau frugal living ini sebenarnya positif dalam rangka untuk menolak konsumerisme dan komersialisasi pasar yang saat ini sudah sangat masif dan itu sangat mengakar,” katanya kepada Alinea.id belum lama ini.
Daya beli masyarakat melemah, ditandai dengan menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Data menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 52 juta orang pada 2023. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pertumbuhan upah riil yang tidak mampu mengimbangi laju inflasi.
Dampak lain dari pelemahan daya beli terlihat dari fenomena makan tabungan alias mantab. Masyarakat mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Per September 2024, rata-rata saldo rekening perbankan dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya sekitar Rp1,8 juta, turun dari rata-rata Rp3 juta pada 2019. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin kesulitan mempertahankan tabungan mereka.
Lebih lanjut, fenomena mantab ini juga berkontribusi pada meningkatnya penggunaan pinjaman daring (pinjol). Data menunjukkan outstanding pinjaman dari fintech lending melonjak dari Rp13,1 triliun pada 2018 menjadi Rp75,60 triliun pada November 2024. Artinya, ketika tabungan terkuras, banyak orang akhirnya beralih ke utang sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang berisiko memperburuk kondisi keuangan mereka di masa depan.
Dampak no buy challenge terhadap ekonomi nasional
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian, menyoroti sisi lain dari tren ini. Dari sudut pandang individu, no buy challenge memang dapat mendorong perilaku keuangan yang lebih sehat, seperti mengelola uang dengan bijak dan menghindari konsumsi berlebihan. Namun, dari sisi makroekonomi, gerakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai informasi, sekitar 54% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi. Jika tren penghematan ini terjadi secara masif, pendapatan sektor ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan tergerus, perputaran uang dalam ekonomi melambat, dan penerimaan pajak dari konsumsi pun menurun.
Hal ini dapat berujung pada penurunan aggregate demand (permintaan agregat), yang berpotensi menyebabkan pengurangan jam kerja, stagnasi upah, hingga PHK. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh sektor ritel dan UMKM, tetapi juga sektor-sektor lainnya yang bergantung pada daya beli masyarakat.
“Jika ada perlambatan konsumsi, bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi jadi tidak optimal,” ujar Eliza kepada Alinea.id beberapa waktu lalu.
Fenomena no buy challenge mencerminkan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Di satu sisi, gerakan ini dapat menjadi strategi adaptasi untuk menghadapi tekanan ekonomi. Namun, jika dilakukan secara luas dan berkepanjangan, tren ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama karena sektor konsumsi memiliki kontribusi besar terhadap PDB.
Solusi untuk masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan perubahan perilaku individu. Diperlukan kebijakan struktural yang lebih adil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung sektor-sektor yang menopang ekonomi nasional. Jika tidak, upaya individu untuk bertahan melalui penghematan hanya akan menjadi solusi sementara di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
Menghadapi tren ini, pemerintah dan regulator perlu berperan lebih aktif dalam mengatasi akar permasalahan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan ekstrem. Menurut Galau, ketimpangan ekonomi dan pemiskinan struktural harus menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni meningkatkan redistribusi ekonomi. Pemerintah perlu mengoptimalkan sistem perpajakan agar tidak semakin membebani kelas menengah, sekaligus meningkatkan pembiayaan bagi sektor produktif berbasis komunitas.
Lalu, mendukung UMKM dan ekonomi lokal. UMKM dan sektor ekonomi berbasis partisipasi lokal harus mendapatkan perhatian lebih melalui subsidi, kemudahan akses permodalan, dan penguatan ekosistem usaha.
Langkah lain, menjaga keseimbangan antara konsumsi dan tabungan. Perlunya edukasi keuangan yang mendorong keseimbangan antara konsumsi dan tabungan agar masyarakat tidak terjebak dalam pola hidup ekstrem—baik konsumtif maupun terlalu menahan belanja hingga berdampak negatif pada ekonomi.
Serta, mengendalikan harga properti dan biaya hidup. Harga perumahan yang semakin tidak terjangkau menjadi tantangan besar bagi generasi muda. Kebijakan perumahan yang lebih inklusif serta pengendalian harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas.