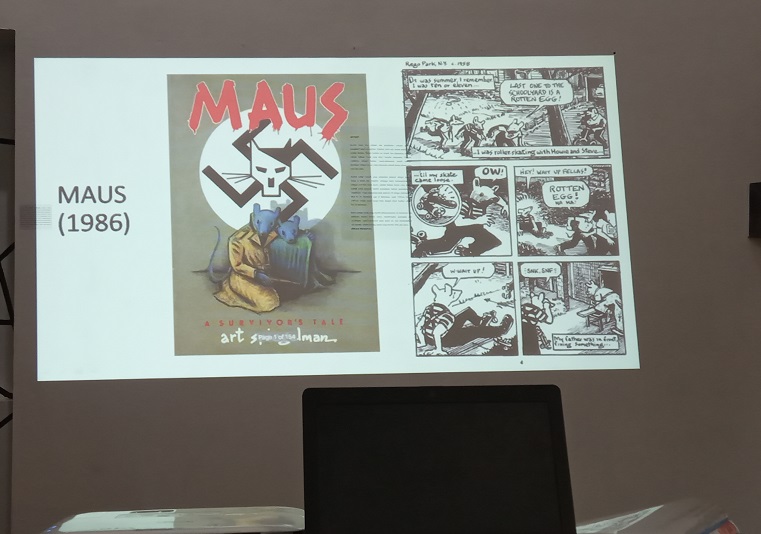Kecebong vs Kampret, fabel politik nihil hikmah
*Penulis dan penikmat sastra. Aktif dalam berbagai kajian sastra dan pesantren. Mengabdi di majelis Surah Sastra Jakarta dan Komunitas Seniman Santri (KSS) Cirebon.
Kecebong dan kampret, dua binatang -yang barang kali- lebih masyhur ketimbang cenderawasih Bhin-Bhin, rusa Bawean Atung, dan badak bercula satu yang dinamai Kaka. Padahal, di wajah lucu tiga hewan terakhir itu, pamor Indonesia akan dipertaruhkan sebagai tuan rumah.
Kabar persiapan pesta olahraga ke-18 sewilayah Asia yang mengusung maskot tersebut masih kalah sepi dibanding dua sebutan yang lahir dari polarisasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kecebong, disasarkan bagi siapa pun yang terkesan menjadi pendukung Joko Widodo. Sedangkan kampret, dirujuk kepada pihak yang berseberangan dengan mereka.
Meski pada dasarnya, penamsilan karakter binatang yang memuai dari persoalan sosial semacam ini bukan barang baru. Tetapi, ada pola terbalik yang pada hari ini penyusunan struktur fabel seperti itu sama sekali tak membawa manfaat, dan cenderung terus merugikan.
Jika dahulu penggunaan karakter binatang sebagai bahan satire agar manusia merasa malu dan pada akhirnya mampu berbuat lebih baik, sekarang, tidak lagi. Pemunculan nama itu tak lebih dari sekadar cemoohan. Minus pesan, nihil hikmah.
Belajar dari hewan
Filsuf Yunani, Aesop dikenal sebagai bapak fabel dunia. Di tangannya, ia pelopori kisah hewan yang memiliki karakter persis manusia. Dongeng yang dihasilkan dari pria kaya yang lahir sekitar 650 sebelum masehi itu dipercaya mampu menjadi rambu tingkah laku di sepanjang waktu. Siapa yang tak kenal istilah 'srigala berbulu domba'? Dari salah satu fabel karya Aesop itu lah, banyak manusia belajar betapa tampilan fisik tak mencukupi apa-apa yang dikandung dalam sanubarinya.
Dalam Semua Berakar Pada Karakter (2007), Ratna Megawati menyebut bahwa tujuan Aesop menggagas fabel adalah melembutkan sindiran. Di masanya, Aesop merasa perlu membentuk sebuah nasihat yang tidak secara tembak langsung memengaruhi tata laku manusia di tengah kehidupan bermasyarakat.
"Aesop melihat tingkah laku binatang mempunyai kemiripan dengan manusia. Ia menginginkan manusia menjadi lebih baik, namun ia menyadari manusia tidak senang kalau secara langsung dikritik perilakunya. Maka, melalui sindiran yang dituangkan dalam kisah-kisah fabel, manusia dapat belajar bagaimana seharusnya manusia berperilaku," tulis Ratna.
Ratna semacam tengah menegaskan kaitan fabel -yang ia yakini sebagai salah satu prdoduk sastra-, dengan kehidupan sosial. Dalam kajian sosiologi sastra, dinamika masyarakat dikenal sebagai cabang reflektif. Artinya, masyarakat dan sastra adalah bagian yang tak terpisahkan dengan sistem komunikasi secara keseluruhan. Termasuk, politik.
Kembali ke perihal serapah kecebong dan kampret, selain keduanya tidak memenuhi unsur penyusunan fabel, tak tampak juga hal tersebut timbul dari upaya reflektif terkait dinamika kehidupan sosial. Keberadaannya murni dari kegagalan memahami konteks persaingan dalam politik demokrasi. Berbeda pula dengan kamus pertarungan "Cicak vs Buaya" yang sumbernya relatif tunggal berupa pendapat publik di saat menyimpulkan timbang-timbang kapasitas dan kekuatan.
Kecebong diterjemahkan sebagai hewan yang menaruh ketergantungan penuh kepada induknya. Sementara kampret, merupakan tuduhan tendensius untuk mengarahkan makna bahwa kelompok bersangkutan gemar mengabaikan etika. Serupa makna denotasinya, kampret, berperilaku mencuri buah dari satu pohon ke pohon lainnya.
Yang jelas, sebutan itu sama-sama bersumber dari orang kedua. Saling serang. Dan belum tentu diamini oleh masing-masing ruang.
Jalan tengah
Beruntung, jika sampai sekarang sastra masih dipercaya sebagai alternatif yang bisa memengaruhi kehidupan sosial-politik di masyarakat. Salah satu turunan sastra, puisi, misalnya, tetap mendapatkan tempat sebagai media strategis guna menyampaikan aspirasi dan gagasan.
Kegaduhan respon atas puisi Sukmawati Sukarnoputri beberapa pekan kemarin, salah satunya. Begitu juga, banyaknya politisi yang justru memanfaatkan sastra sebagai jalan main aman untuk mengedepankan kritik bahkan nyinyiran, sebenarnya bukan kabar yang buruk-buruk amat.
Paling tidak, ada kepercayaan yang masih terawat dari ucapan yang pernah dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy. Yakni sebuah jargon, ketika politik kotor, puisi menyucikannya. Bila bengkok, sastra meluruskannya.
Entah benar atau tidak cara menerapkannya, setidaknya ada dukungan dan legitimasi bahwa karya sastra tidak boleh lahir mengambang. Sebagaimana keyakinan orang-orang terdahulu yang berkeyakinan bahwa sastra bisa dijelmakan sebagai senjata. Dasar logis itu sebenarnya sudah dibangun sejak zaman Plato. Ia mendefinisikan sastra sebagai sebuah hasil dari tiruan ide kehidupan sosial.
Faruk HT dalam Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-modernisme (1994) bilang, Plato berpendapat apabila dunia dalam karya sastra membentuk diri sebagai sebuah dunia sosial, maka dunia tersebut adalah sebuah tiruan dari dunia sosial yang nyata dan dipelajari oleh sosiologi.
Sayangnya, dunia sastra saat ini sedikit banyak turut terdampak dari pembelahan politik di masyarakat. Terlebih, belum reda sisa persoalan 2014, masyarakat sudah ditimpa persoalan serupa menyongsong Pilpres 2019.
Masyarakat butuh kehadiran sastra sesuai khitahnya sebagai jalan tengah. Penyadaran bahwa dunia menghadirkan banyak alternatif, bukan cuma Jokowi-Prabowo, hitam-putih, salah-benar, atau kecebong-kampret; makin menjadi kebutuhan mendesak.
Caranya, memahami karakter utuh nama binatang yang selama ini hanya diseret sebagai bahan hinaan. Melalui sejenis fabel politik, masyarakat bisa menumbuhkan rasa malu untuk sekadar saling serang, mirip tingkah mereka yang berada di hutan.