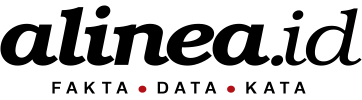Terulang setiap 1 Mei, buruh dari lintas korporasi di Indonesia melakukan refleksi atas ketenagakerjaan mereka, dengan berbagai cara, salah satunya turun ke muka umum dengan menyampaikan aspirasi atau tuntutan. Hanya saja, aktivitas ini tidak pernah benar-benar berhasil karena pada tahun berikutnya tuntutan yang sama akan diulang.
Ada yang terlupakan dalam momentum tahunan ini, membawa gerakan buruh ke ranah politik yang lebih jelas alur aspirasinya. Tetapi, jika salah menghitung maka gerakan akan terjerumus dalam ruang politis. Tentu, politik dan politis memiliki perbedaan. Politik adalah kebijakan, sementara politis adalah kepentingan.
Besarnya asosiasi buruh –dengan berbagai bendera—tentu memiliki potensi dijadikan target politis para elit, terlebih dalam momentum menjelang Pemilu. Sayangnya, peringatan buruh bertanggal seusai Pemilu. Sehingga bargaining power buruh sedikit terdistorsi. Meskipun demikian, buruh tetap saja memiliki peluang untuk menuntut hak yang lebih baik, dan tentu lebih diterima oleh lebih banyak buruh lainnya.
Sejauh ini, mencermati tuntutan buruh selalu didominasi soal upah. Sehingga buruh memaklumi diri sendiri bahwa tenaga mereka, harus dikonversi dalam bentuk upah (materialisme). Padahal, seharusnya tuntutan mereka beranjak lebih pada jaminan sosial (utilitarianisme), yaitu upaya untuk menjamin hak atas pekerja terpenuhi secara proporsional sesuai kewajiban.
Kesetaraan
Utilitarianisme, sebagimana dikatakan oleh pemikir Jeremy Bentham (1748), merupakan pandangan filsafat yang mengedepankan segala tindakan atau perjuangan, memiliki imbas pada kebermanfaatan sosial (social benefit). Jika demikian, inilah momentum buruh dalam memperbarui tuntutan, harus lebih pada upaya mendapatkan manfaat sosial yang berjangka panjang.
Salah satu ide penting menuntut hak pekerja, adalah kesetaraan. Hal ini bisa ditafsirkan dalam berbagai platform, ekonomi, dan kehidupan sosial. Termasuk dengan perlakuan proporsional bagi pekerja perempuan. Dengan pemikiran yang demikian, buruh seharusnya bisa lebih maju sekaligus produktif.
Sementara upah, terbatas. Berapapun nominal yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetap saja tidak akan cukup mengganti pekerjaan para buruh, karena upah bersifat jual beli, materialisme memupus adanya hubungan yang setara antara pekerja dan korporasi.
Sementara jaminan sosial, adalah pegangan berjangka panjang karena tidak bernilai jual beli, tetapi bersifat hak dan kewajiban yang saling melayani.
Karl E. Weick dalam Organizing Theories (1996) berpandangan, setiap individu akan mempelajari lingkungan secara proporsional. Menyeleksi apapun ia lihat dan rasakan, kemudian dikonversi kepada tindakan untuk menyamai apa yang ia dapat dari lingkungan.
Lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembangnya individu, akan dijaga oleh individu tersebut tanpa mementingkan nilai-nilai pragmatis, individu secara sukarela akan menjadi pengabdi bagi lingkungan. Sebaliknya, ketika lingkungan tidak memberikan manfaat, maka individu akan cenderung menjadi perusak bagi lingkungan yang sama.
Mempelajari teori di atas, maka bisa disimpulkan apabila korporasi tidak memberikan layanan yang baik kepada pekerja, maka pekerja akan kehilangan selera untuk menjaga ekosistem korporasi tersebut. Imbasnya, produktivitas menurun, dan keduanya akan saling berseberang dalam menentukan titik temu.
Buruh meminta nominal upah yang terus meningkat, sementara korporasi semakin terpuruk ketika terlalu besar menentukan upah. Kondisi ini yang sedang terjadi, itulah sebabnya buruh harus memulai tradisi baru.
Membawa kepentingan ketenagakerjaan ke ranah politik yang akomodatif, menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang membela, salah satunya jaminan sosial yang meliputi hak hidup layak pekerja serta berkelanjutan. Dan tentu yang demikian itu tidak selalu berkaitan nominal upah.
Beberapa hal yang mungkin belum dirasakan oleh seluruh buruh karena minimnya kebijakan yang memaksa korporasi menyediakan, jaminan kesehatan dan keamanan kerja, penyediaaan ruang khusus bagi pekerja perempuan, ruang khusus penjagaan anak-anak pekerja, termasuk jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan keselamatan.
Akhirnya, refleksi dari politik buruh ini harus dibawa ke ruang lingkup yang lebih dialogis dan berkelanjutan. Pemerintah menyediakan kebijakan yang menjembatani antara hak dan kewajiban korporasi dengan pekerja.
Sebaliknya, pekerja juga dibebankan kewajiban sesuai dengan hak yang dipenuhi oleh korporasi. Jika rotasi hubungan pekerja, kebijakan, dan korporasi, terpenuhi. Maka industri di Indonesia memiliki potensi maju lebih besar dibandingkan dengan berkutat soal upah.