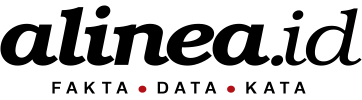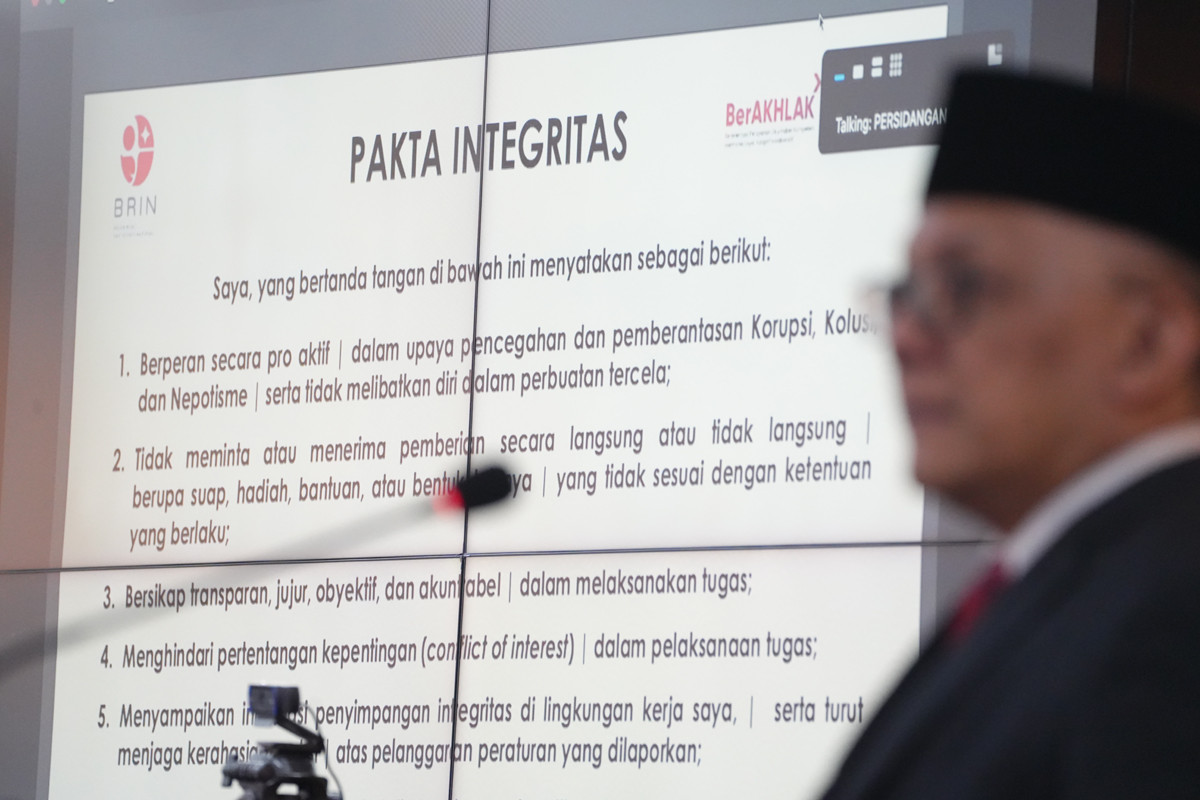Akurasi Tata Batas Menjamin Kawasan Hutan Bebas Okupasi: Sebuah Tanggapan Atas Artikel Guru Besar IPB
Artikel yang ditulis oleh seorang Guru Besar IPB dengan Judul “Penetapan Kawasan Hutan Tak Akurat, Masyarakat Kena Imbas” pada meda online Sawit.com pada 16 Juni 2025, membuat terperangah atau garuk-garuk kepala para rimbawan terkait substansi yang ditulisnya. Hal yang ditulisnya terutama berkaitan dengan skala peta dan penggunaan spidol untuk proses pemetaan, sehingga berdampak kepada masyarakat.
Tulisan ini merupakan tanggapan penulis atas artikel yang ditulis Guru Besar IPB tersebut dengan penekanan pada proses pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan PP No. 44/2004 (Perencanaan Hutan) disebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
Oleh karena itu, tujuan penulisan paper ini adalah, untuk membahas dan mendiskusikan terkait: (i) penunjukan kawasan hutan, (ii) penataan batas, (iii) pemetaan kawasan hutan, (iv) penetapan kawasan hutan, dan (v) dampak penetapan kawasan hutan terhadap masyarakat.
Penunjukan Kawasan Hutan
Sebelum bicara soal penunjukan kawasan hutan dan agar guru besar tersebut, memahami konteksnya dengan benar, maka perlu juga dibahas juga terkait definisi Kawasan hutan sebagaimana merujuk pada UU No. 41/1999 (Kehutanan) Pasal 1 ayat (3). Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Walaupun di UU No. 41/1999 tidak didefinisikan apa itu hutan tetap, tetapi pada PP No. 23/2021 (Penyelenggataan Kehutanan) telah didefinisikan hutan tetap sebagai hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap.
Definisi hutan tetap tersebut dirasakan masih terlalu sempit jangkauannya, maka penulis mencoba mendefinisikan hutan tetap adalah hutan negara, hutan adat, hutan hak yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan yang harus dijaga kelestarian dan keberadaannya. Konsekuensi dari penetapan hutan tetap, maka pemerintah harus menetapkan insentif (penghargaan) bagi yang menjaga hutan dan disinsentif (hukuman) bagi yang merusak hutan atau mengokupasi hutan secara ilegal.
Penunjukan kawasan hutan adalah tahapan awal yang harus diilakukan dalam rangkaian proses pengukuhan hutan dan harus dilakukan secara bertahap, berurutan dan tidak bisa melompat-lompat dari tahapan 1 (penunjukan) ke tahapan 3 pemetaan.
Menurut Susetyo (2021) penunjukan dan atau penetapan kawasan hutan oleh pemerintah (menteri yang menangani bidang kehutanan) sebagai legalitas hutan negara secara hukum (de jure) tidak mudah dan sederhana karena membutuhkan proses dan waktu yang panjang.
Pada waktu itu, proses penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan membuat Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang ditandatangani oleh pemeintah pusat dan pemerintah provinsi. Pelaksanaan TGHK itu dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara kawasan hutan agar tidak mudah dan cepat untuk dialihfungsikan oleh pemerintah-pemerintah daerah, walaupun sebenarnya sudah ada peta kawasan hutan dalam bentuk register hutan yang merupakan peninggalam jaman kolonial Belanda.
Penunjukan kawasan hutan versi TGHK ini, sebenarnya diupdate setiap lima tahun dengan merevisinya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dan berkembang di lapangan. Sebagai contoh sejarah penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara (Siregar, 2021) adalah sebagai berikut:
1. Sejarah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Pertama kali pada Era Masa Pemerintahan Belanda dimulai 1916 sampai dengan 1944 dengan luas ± 2.121.500,02 ha.
2. Setelah Indonesia merdeka, penunjukan kawasan hutan pertama di Provinsi Sumut sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 Tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara Seluas ± 3.780.132.02 ha atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
3. Pada tahap ketiga dilakukan yang dikenal dengan istilah Paduserasi antara TGHK dan RTRW Provinsi Sumut 2017 dengan luas ± 3.867.761 ha.
4. Selanjutnya tahap keempat, penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor SK.44/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 ha.
5. Tahap kelima, penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumut berdasarkan SK Menhut Nomor SK.579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.055.795 ha yang selanjutnya adanya perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan (Hasil Penataan Batas) Provinsi Sumut sampai Tahun 2017 dengan luas ± 3.001.772 ha (Sumber Data Kementerin Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Berdasarkan fungsi Kawasan hutan pascapenataan batas di Provinsi Sumut terbagi atas Hutan Suaka Alam (Hutan Konservasi) seluas ± 420,721 ha, Hutan Lindung seluas ± 1.194.432 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 634.626 ha, Hutan Produksi Tetap seluas ± 673.131 ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 78.861 ha.
Namun kenyataannya, kawasan hutan di Provinsi Sumut sebagian besar telah banyak mengalami perubahan baik itu perubahan penutupan lahannya dan perubahan penggunaan lahannya.
6. Data Penutupan Lahan Tahun 2019 Provinsi Sumut berdasarkan hasil Citra Resolusi Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk lahan yang berhutan adalah seluas ± 1.755.016 ha yang terdiri dari Hutan Lahan Kering Primer seluas ± 577.061 ha, Hutan Lahan Kering Sekunder seluas ± 945.795 ha, Hutan Mangrove Primer ± 1.451 ha, Hutan Mangrove Sekunder seluas ± 36.571 ha, Hutan Rawa Primer seluas ± 558 ha, Hutan Rawa Sekunder seluas ± 60.332 ha dan Hutan Tanaman seluas ± 133.246 ha. Luas penutupan lahan dengan tipe berhutan seluas ± 1.755.016 ha ternyata lebih kecil dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dengan luas ± 3.001.772 Ha.
Sejarah menujukkan, penunjukan kawasan hutan telah mengalami beberapa perubahan luasan dari zaman Belanda hingga penetapan 2014 (SK Menhut No. 579/2014) dan hasil tata batas 2017 serta hasil citra resolusi tinggi 2019. Disamping itu, proses penunjukan kawasan hutan tidak terlepas dari Keputusan Mahkamah Konsitusi No. 45/PUU-IX/2011 yang memutuskan bahwa frasa “penunjukan dan/atau” bertentang dengan UUD 1945, sehingga kata ataunya dicoret.
Hal tersebut, menjadikan bahwa proses yang sedang berjalan adalah pengukuhan walaupun masih di tahap 1 (penunjukan) dan dapat menjadi satu kesatuan pengukuhan, sehingga tidak juga dapat disimpulkan bahwa proses penunjukan tersebut tidak berlaku.
Jadi, jika dikatakan bahwa penunjukan kawasan hutan telah meminggirkan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Guru Besar IPB tidak sepenuhnya benar karena pemerintah cq. Kementerian Kehutanan telah mengakomodir dan mempaduserasikan dengan RTRWP yang ada. Apalagi perubahan RTRWP dimungkinan untuk dilakukan perubahan dengan rentang waktu lima tahunan.
Seyogianya memang KLHK (sejak 2024 KLHK kembali menjadi Kementerian Kehutanan) menetapkan kembali kawasan hutan di Sumut sejak ada perubahan data kawasan hutan 2019 berdasarkan citra resolusi tinggi, sehingga tidak ada pertanyaan lagi kenapa penetapan kawasan hutan Sumut terbaru belum juga terbit.
Penataan Batas
Penataan batas kawasan hutan merupakan langkah kedua dari proses pengukuhan kawasan hutan. Langkah pertamanya adalah penunjukan kawasan hutan. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.
Sedangkan kegiatan penataan batas terdiri atas pelaksanaan tata batas dan pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang.
Menurut data 2018, tata batas kawasan hutan yang telah ketemu gelang mencapai 81%. Persyaratan ketemu gelang ini yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tata batas dan pembuatan BATB nya. Penataan Batas (81%) Ini pun baru tata batas luar antara kawasan hutan dan non kawasan hutan, tetapi belum menyentuh tata batas antar fungsi kawasan (hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi) maupun tata batas dalam fungsi kawasan (hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi (Susetyo, 2021).
Dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, kegiatan penataan batas yang paling lama dan rumit untuk dilaksanakan oleh para pelaksana. Kegiatan tata batas membutuhkan waktu lama karena kegiatan penataan batas kawasan hutan dilakukan langsung di lapangan (ground chek) untuk melakukan pemancangan patok batas sementara dan pemasangan pal batas permanen yang dilengkapi dengan lorong batas yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Sebagaimana telah dijelaskan lamanya waktu penataan batas, dimana salah satu penyebabnya adalah karena persyaratan ketemu gelang (titik awal dimulai tata batas harus bertemu di titik yang sama ketika mengukur titik akhir tata batas) yang memang perlu dilakukan dengan akurasi yang sangat tinggi dengan alat Theodolit. Di samping itu, juga perlu kesepakatan oleh para pihak terhadap tata batas yang sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan proses penandatangan BTPBnya.
Pemetaan Kawasan Hutan
Kegiatan pemetaan kawasan hutan merupakan langkah ketiga dari proses pengukuhan kawasan hutan. Hasil penataan batas (langkah kedua) kemudian dipindahkan ke peta tata batas dengan skala 1:10.000. Skala 1:10.000 mengartikan bahwa panjang 1 cm di peta merefleksikan panjang 10.000 cm atau 100 meter di lapangan.
Alat pertama yang digunakan dalam teknologi perpetaan adalah planimeter. Tikkanen (2025) menjelaskan bahwa planimeter adalah instrumen matematika untuk mengukur secara langsung luas yang dibatasi oleh kurva tidak beraturan, dan dengan demikian mengukur nilai integral tertentu. Instrumen pertama yang menggunakan prinsip cakram dan roda untuk mengintegrasikan, ditemukan pada 1814 oleh JHHermann, seorang insinyur Bavaria. Kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga akhirnya menemukan planimeter digital.
Penulis masih ingat ketika pada 1985 mengajar mata ajara perpetaan di Balai Latihan Kehutanan Samarinda, sudah menggunakan planimeter dengan alat tulis Rapido 0,5 mm. Sehingga rasanya, berlebihan jika dikatakan oleh guru besar kalau pembuatan peta kehutanan menggunakan spidol.
Spidol biasa digunakan untuk memperjelas peta yang sudah ada di lapangan, jadi keliru besar kalau peta kehutanan digunakan spidol untuk penggambaran peta kehutanan. Mungkin yang dimaksud menggunakan spidol jika digambar-gambar pada peta kerja yang ada.
Hingga pertengahan abad ke-20 (1980-an) di mana teknologi GIS dan perangkatnya ditemukan, maka teknologi planimeter sudah ditinggalkan. Berdasarkan Kejora (2024) Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah salah satu teknologi yang telah merevolusi cara manusia memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi spasial. Teknologi ini memungkinkan bagi para pengguna untuk mengintegrasikan data berbasis lokasi dengan berbagai jenis informasi lainnya, menghasilkan wawasan yang mendalam untuk berbagai aplikasi.
Konsep GIS modern mulai muncul seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Salah satu tonggak penting dalam sejarah GIS adalah proyek “Canadian Geographic Information System” (CGIS) yang dimulai pada 1960-an. Proyek ini dirancang untuk membantu pemerintah Kanada mengelola data sumber daya alam mereka secara lebih efisien. Pada Dekade 1970-an hingga 1990-an merupakan periode transformasi besar dalam teknologi GIS. Pada periode ini, GIS mulai diadopsi oleh berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan akademisi (Kejora, 2024).
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka argumentasi pembuatan peta dilakukan dengan menggunakan spidol terbantahkan karena sejak 1990-an, sudah mulai digunakan teknologi GIS untuk perpetaan. Kemungkinan besar, Departemen Kehutanan juga telah memanfaatkan teknologi GIS ini untuk pemetaan kawasan hutan pada tahun yang sama (1990-an).
Persoalan jika masih ada peta dengan skala 1:250.000 itu dalam rangka melihat secara utuh peta dalam sebuah peta lanskap, misalnya peta kawasan hutan di sebuah provinsi dengan maksud akan terlihat secara jelas batas-batas kawasan hutannya. Jika ingin lebih detail tata batasnya dapat dilihat peta kawasan hutan yang tersedia sebagai lampiran di BATB.
Memang seharusnya dengan kemajuan dan perkembangan teknologi GIS, Kemenhut sudah harus meninggalkan peta-peta dengan skala yang kecil (lebih dari 1: 250.000) sehingga tidak menimbulkan persepsi di mata para pengguannya. Menurut Laia (2024) Badan Informasi dan Geospasial (BIG) saat ini telah melakukan pemutakhiran peta sawit nasional pada skala 1:50.000 pada 2023 dan akan diintegrasikan dengan program Satu Peta, sehingga Kemenhut juga harus menggunakan peta kawasan hutan yang sama dengan yang dibuat oleh BIG. Hal ini untuk menghindari terjadi perbedaan penafsiran 1 titik di peta yang bisa berarti beberapa meter di lapangan. Apalagi ketika peta-peta tersebut digunakan dalam berbagai overlay dari penentu kebijakan, makanya hasilnya akan berbeda di lapangan dan berpeluang menciptakan konflik tenurial di lapangan.
Penetapan Kawasan Hutan
Setelah tahap 1 (penunjukan kawasan hutan), tahap 2 (penataan batas), dan tahap 3 (pemetaan), maka tahap ke 4, yaitu penetapan kawasan hutan dilakukan dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Penetapan kawasan hutan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena kawasan hutan adalah “milik” negara dan kenapa Menteri yang menetapkan, Akhirnya terbit Keputusan MK No. No. 34/PUU-IX/2011, yang menyatakan, hutan bukan dimiliki oleh negara, tetapi dikuasai oleh negara dan MK menjelaskan apa makna dibalik kata “dikuasi”.
Di samping itu, MK juga menegaskan, penguasaan hutan oleh negara tetap harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat lainnya, terutama hak atas tanah. MK menegaskan, hutan adat bukan termasuk hutan negara, melainkan hutan hak yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Berdasarkan penjelasan di atas maka pendapat Guru Besar IPB bahwa penetapan kawasan hutan tidak akurat dan masyarakat terkena imbas tidak memiliki dasar argumentasi ilmiah yang jelas. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut: (1) bahwa perkembangan teknologi GIS telah berkembang pada 1990-an, sehingga menjadikan penetapan kawasan hutan menjadi lebih akurat berikut dengan sistem penetaannya dan (2) sejak 2011 (Putusan MK No. 34/2011) sudah menjelaskan bahwa penguasaan hutan oleh negera perlu memperhatikan hak-hak masyarakat.
Ada yang perlu juga diketahui oleh Guru Besar IPB, bahwa KLHK sudah menetapkan SK Hutan Adat sebanyak 138 unit hutan adat per Juli 2024 dengan luas keseluruhannya mencapai 265.250 hektare (Ma’arif, 2024). Pemberian hutan adat tersebut menjadi kewenangan penuh masyarakat adat untuk mengelola hutannya sesuai dengan fungsi kawasan hutannya, tetapi jika masyarakat ada ingin merubah fungsi kawasan hutannya, maka perlu dilakukan dengan persetujuan menteri sebagaimana bunyi putusan MK No. 35/2012 (Subarudi, 2014).
Dampak Penetapan Kawasan Hutan terhadap Masyarakat
Argumentasi Guru Besar IPB bahwa penetapan kawasan hutan yang tidak akurat berdampak pada masyarakat yang terkena imbasnya (Gunawan, 2025). Pernyataan ini sesat pikir, karena persoalan penetapan kawasan hutan harus memenuhi persyaratan “clear and clean” (jelas dan tidak ada klaim kepemilikan), sehingga jika sudah ditata batas dan ada masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan ini dikenal sebagai perambahan hutan.
Sejak 10 tahun lalu, para perambah hutan baik di segala fungsi kawasan hutan menjadi sangat marak karena ada pesan tersirat bahwa jangan sampai perambah itu dilaporkan dan dilakukan proses pidana karena masyarakat itu adalah mitra KLHK. Hal ini terjadi karena rezim pemerintahan saat itu sedang bergembira menggalakan program perhutanan sosial dengan alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta ha dalam lima tahun pemerintahan. Target 12,7 juta ha itu terlalu bombastis, sehingga jangka waktu target pencapainnya diulang menjadi 10 tahun dan tetap tidak tercapai hingga pemerintahan baru terbentuk.
Sebenarnya. masih dapat dikatakan wajar bila masyarakat yang merambah dengan luasan 5-10 hektare. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki alat Global Positioning System (GPS) sehingga mereka tidak mengetahui bahwa itu kawasan hutan, tetapi banyak juga masyarakat perambah mengetahu betul bahwa lahan yang digarapnya itu kawasan hutan. Hal yang tidak wjar dan kurang ajar adalah perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit (PKS) yang memiliki alat GPS, tetapi masih saja merambah kawasan hutan dengan luasan yang mencapai ratusan dan ribuan hektar sebagai hasil mengokupasi kawasan hutan secara illegal.
Sebagai contoh Surya Darma, pemilik PT Dulta Palma Group terbukti telah mengokupasi kawasan hutan sejak 1994 menjadi PKS dan divonis 16 tahun penjara, membayar denda Rp1 miliar, serta mengembalikan kerugian negara senilai Rp2,2 triliun karena (Tempo.co, 2025). Akhirnya Kejaksaan Agung menyerahkan lahan sitaan kebun sawit dari hasil korupsi PT Duta Palma seluas 221 ribu hektare kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi lahan dalam melaksanakan program pemerintah swasembada pangan (Beneskeri, 2025).
Saat penulis menjadi saksi ahli dalam kasus korupsi PT Dulta Palma Group, Ketua Majalis Hakim meminta untuk menjelaskan mengapa perusahaan dikenai sanksi pidana, walaupun perusahaan sudah memiliki izin lokasi (ilok), punya izin usaha perkebunan (IUP) dan juga memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Penulis menegaskan kepada Ketua Majelis, apapun yang dimiliki perusahaan (Ilok, IUP dan HGU), jika perusahaan beroperasi di kawasan hutan harus memiliki izin dari Menteri Kehutanan. Jika tidak memiliki izin berarti perusahaan tersebut beroprasi secara ilegal di kawasan hutan.
Sebenarnya penulis sudah mengungkapkan mengapa kawasan hutan begitu mudah diokupasi oleh perusahaan PKS, karena mereka menggunakan prinsip “lebih baik minta maaf daripada meminta izin”. Mereka sudah mengkalkulasi secara bisnis berapa denda yang harus dibayarkan dengan skema “keterlanjuran” yang dirasakan lebih rendah daripada biaya mengurus izin resmi. Jadi harap maklum, luas PKS dari 3, 7 juta hektare dan sekarang telah meningkat kali lipat menjadi 17,3 juta ha yang, hampir 1,5 kali luas Pulau Jawa (Laia, 2024). Luas PKS itu sebagian besar merupakan hasil pelepasan kawasan hutan yang telah diokupasinya secara illegal.
Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali terbit sertifikat hak milik (SHM) di kawasan hutan seperti di Nusa Tenggara Barat, di Suaka Margawatwa Langkat, Sumut dan Taman Nasional Teso Nilo, Riau, maka untuk mencegah terjadi sertifikasi kawasan hutan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka seyogianya pengukuhan hutan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, tetapi ditindaklanjuti dengan didaftarkan juga ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menghindari terjadinya proses sertifikasi lahan di kawasan hutan dan juga untuk keamanan kawasan hutan.
Keamanan kawasan hutan rentan karena beberapa kelemahan dalam pengawasan (pengamanan dan penjagaan) kawasan hutan. Kewenangan pemerintah dalam pengawasan baik ketaatan aparat penyelenggara maupun pelaksana terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan kurang memadai.
Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, jumlah aparat jagawana (polisi kehutanan) seluruh Indonesia pusat dan daerah diperkirakan 7.000 orang, tidak sebanding dengan luas kawasan hutan 125,2 juta hektare yang harus mereka awasi. Itu berarti 1 jagawana menjaga 18.000 hektare kawasan hutan. Idealnya, rasio 1:1.000 hektare.
Artinya, masih membutuhkan 25.000 jagawana di tengah keuangan negara yang terbatas. Dapat disimpulan sepanjang rasio penjaga dan luas kawasan hutan masih timpang, perambahan, pembalakan, penambangan liar, hingga konflik tenurial akan terus terjadi. Melibatkan masyarakat di sekitarnya salah satu solusi terbaik menjaga hutan bersama-sama dan mengembalikan lagi dan merevitalisasi kembali fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolan kawasan hutan di tingkat tapak.
Penutup
Tulisan ini sebagai upaya menjelaskan terkait penetapan kawasan hutan yang disinyalir dilakukan tidak akurat dan menyebabkan masyarakat terkena imbasnya sudah semakin jelas bahwa semua argumen yang diungkap oleh Guru Besar IPB gugur dengan sendirinya.
Oleh karena itu, mari kita membuat pernyataan yang kondusif, jika memang sistem pengelolaan hutan itu keliru sebutkan dimana letak kekeliruannya dan mari didiskusikan bersama.
Perlu juga diingat oleh semua pemangku kepentingan betapa pentingnya fungsi dan keberadaan hutan yang harus dikelola secara bijaksana dan bukan menjadi sumber mencari cuan semata dengan menetapakan izin-izin pertambangan atau proyek Strategis Nasional (PSN) yang sembrono di berbagai fungsi kawasan hutan, ingat dan simak renungan ini: “Jika suatu saat pohon terakhir ditebang dan setetes air yang tersisa, maka saat itu baru terdasarkan bahwa uang tidak ada gunanya lagi”.
Daftar Pustaka
Binekasri, R. 2025. Kejaksaan Serahkan 221.000 Hektare Lahan Sawit Kasus Duta Palma ke BUMN. https://www.cnbcindonesia.com/market/20250310111859-17-617145/kejaksaan-serahkan-221000-hektar-lahan-sawit-kasus-duta-palma-ke-bumn.
Gunawan, I. 2025. Guru Besar IPB: Penetapan Kawasan Hutan Tak Akurat, Masyarakat Kena Imbas. https://sawitindonesia.com/guru-besar-ipb-penetapan-kawasan-hutan-tak-akurat-masyarakat-kena-imbas/.
Kejora, B, 2024. Sejarah GIS: Perkembangan Teknologi Geospasial dari Awal Hingga Menjadi Sistem Canggih. https://www.technogis.co.id/sejarah-gis-perkembangan-teknologi-geospasial-awal-hingga-sistem-canggih.
Laia, K. 2024. Luas Kebun Sawit Nasional Kini Hampir 1,5 Kali Pulau Jawa. https://betahita.id/news/detail/10083/luas-kebun-sawit-nasional-kini-hampir-1-5-kali-pulau-jawa.html?v=1712101862.
Ma’arif, N. 2024. Per Juli 2024, KLHK Sudah Tetapkan 136 Unit Hutan Adat Seluas 265.250 Ha. https://news.detik.com/berita/d-7488394/per-juli-2024-klhk-sudah-tetapkan-136-unit-hutan-adat-seluas-265-250-ha.
Mahkamah Konstitusi. 2012.Penguasaan Hutan oleh Negara Juga Lindungi Hak Masyarakat Atas Tanah. https://www.mkri.id/index.php?page= web.Berita&id=7256&menu=2.
Siregar, T. 2021. Implementasi Kebijakan Peleapasan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (Tora)” (Studi Kasus 13 Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara). https://tumpak-siregar.blogspot.com/2021/04/implementasi-kebijakan-pelepasan.html/
Subarudi. 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis.Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 11 No. 3, Desember 2014 : 207 - 224.
Susetyo, P. D. Legalitas Kawasan Hutan. https://www.forestdigest.com/detail/1154/apa-itu-kawasan-hutan.
Tempo.co. 2025. Sidang Korupsi Korporasi, Surya Darmadi Duduk Sebagai Terdakwa. https://www.tempo.co/hukum/sidang-korupsi-korporasi-surya-darmadi-duduk-sebagai-terdakwa-1231680.
Tikkanen, A. Planimeter. https://www-britannica com.translate.goog/science/planimeter. Diunduh pada Tanggal 22 Juni 2025.