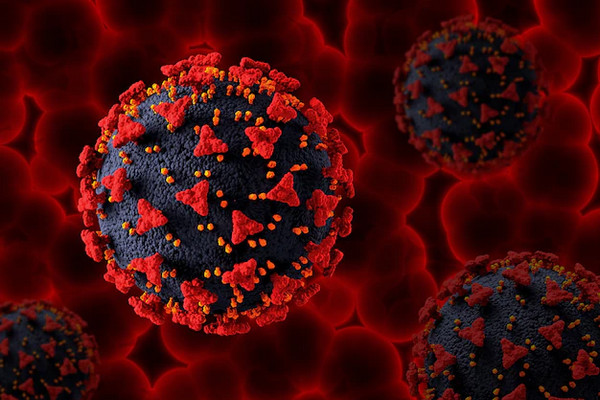Kisah para penyintas Covid-19 dan perjuangan melawan stigma
Selama sepekan, mulai 28 September-6 Oktober 2020, Syefri Luwis mesti mengisolasi diri di rumah. Hasil tes swab menunjukkan ia terpapar virus SARS-CoV-2 penyebab Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Ia menduga, tertular virus itu dari sebuah rumah sakit. Sebelumnya, ia ke rumah sakit untuk menemani ibunya yang dirawat karena Covid-19.
“Padahal saya hanya menunggu dari luar runagan. Menunggu kabar dari dokter,” kata dia saat dihubungi, Minggu (24/10).
Peneliti sejarah kesehatan dan penulis buku Epidemi Penyakit Pes di Malang 1911-1916 (2020) itu mengatakan, ia tidak bergejala sama sekali alias orang tanpa gejala (OTG).
“Hanya badan seperti akan sakit, tapi tidak sampai sakit,” ujarnya.
Di rumah, ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ketika terpapar Covid-19, ia memisahkan segala sesuatu, seperti pemakaian kamar mandi, agar ayahnya tak ikut terlular.
Selama isolasi mandiri, ia rajin mengonsumsi makanan berempah, ikan laut, vitamin C dan D, serta minum minuman tradisional.
“Vitamin sudah saya siapkan sendiri sebelumnya. Karena saya paham penyakit ini, saya selalu menyiapkan dan mengonsumsi vitamin di rumah,” katanya.
Selain Syefri, dalam diskusi daring “Perjuangan Penyintas Melawan Covid-19” di kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (19/10), tiga penyintas Covid-19 lainnya mengisahkan pengalaman terkait penyakit ini.
Salah satunya bankir dan pengusaha, Arwin Rasyid. Ia mengaku terkecoh dengan penyakit ini. Ia merasa hanya demam biasa, saat awal terpapar Covid-19.
Ia mengatakan, terpapar Covid-19 saat berlibur di Bali bersama koleganya. Pada 11 September 2020, ia merasa demam di malam hari.
“Saya pikir demam biasa karena tidak ada tanda-tanda Covid-19, seperti pilek, sakit tenggorokan, dan hilangnya indera penciuman,” kata dia dalam diskusi itu.
Namun, di hari berikutnya, demam itu tak kunjung hilang. Hingga akhirnya, ia memutuskan kembali ke Jakarta. Di Jakarta, ia melakukan tes swab. Hasilnya, positif Covid-19.
“Teman-teman saya di Bali, enam orang semuanya kena Covid-19,” tuturnya.
“Waktu itu, kami makan bersama, tak pakai masker, duduk dekat-dekat.”

Bagaimana melawan stigma?
Perjuangan penyintas Covid-19 bukan hanya berusaha untuk sembuh, tetapi juga melawan stigma dari sejumlah warga. Bahkan, stigma juga dilekatkan oleh tenaga kesehatan.
Misalnya, pada Maret 2020, para tenaga kesehatan, termasuk perawat dan dokter Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Jakarta, sempat mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan karena menangani pasien Covid-19. Akibatnya, mereka memilih pergi dari indekos dekat rumah sakit tempat mereka bertugas.
Syefri pun merasa, lingkungan tempat tinggalnya melakukan stigma terhadap dirinya. Ia mengatakan, tetangganya takut bertemu. Bahkan ketika ia sudah dinyatakan negatif Covid-19.
“Padahal saya juga hanya di rumah saja. Menyebalkan sekali,” kata salah seorang warga Pasar Rebo, Jakarta Timur itu.
Saat ia keluar rumah, ia melihat beberapa tetangganya langsung masuk ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Syefri menilai, perlakuan seperti ini akibat sosialisasi pemerintah tentang pasien Covid-19 tak sampai ke lapisan bawah.
Menurut World Health Organization (WHO) dalam terbitannya “Social stigma associated with Covid-19: A guide to preventing and addressing social stigma”, stigma terkait Covid-19 dilandasi tiga faktor utama, yakni Covid-19 adalah penyakit baru dan masih banyak orang yang belum mengetahuinya, seseorang kerap takut dengan hal-hal yang tak diketahuinya, dan mudah mengaitkan ketakutan terhadap orang lain.
“Maklum, ada kebingungan, kecemasan, dan ketakutan di masyarakat. Sayangnya, faktor-faktor ini juga memicu stereotip yang merugikan,” tulis WHO dalam laporan tersebut.
WHO pun menyebut, stigma bisa mendorong orang untuk menyembunyikan penyakitnya untuk menghindari diskriminasi, mencegah orang mencari perawatan kesehatan dengan segera, serta mencegah mereka mengadopsi perilaku hidup sehat.
“Stigma dapat merusak kohesi sosial dan mendorong kemungkinan isolasi sosial, yang mungkin saja terjadi, serta berkontribusi pada situasi di mana virus lebih banyak, kemungkinan besar menyebar,” tulis Who.
“Ini bisa menghasilkan lebih banyak masalah kesehatan yang parah dan kesulitan mengendalikan wabah penyakit.”
Ketua Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia (JRPI) Irmansyah mengatakan, stigma timbul dari persepsi yang dibentuk dari pengetahuan masyarakat sendiri. Menurutnya, masing-masing anggota masyarakat memiliki preferensi sendiri terhadap sebuah berita atau peristiwa.
“Hanya, kita tahu, yang namanya berita yang negatif justru yang paling menarik. Masyarakat juga cenderung senang menangkap berita-berita seperti itu,” kata dia saat diskusi daring bertajuk “Penguatan Sistem Sosial Penanganan Penyintas Covid-19”, Selasa (20/10).
“Yang banyak dikhawatirkan stigma oleh penderita itu perilaku dari lingkungan.”
Sementara Nurul Eka Hidayati dari Independent Pekerja Sosial Profesional Indonesia, dalam diskusi yang sama menuturkan, munculnya stigma di masyarakat karena rasa takut yang muncul dari ketidaktahuan.
“Ini kan sesuatu yang baru. Jadi, ketidakpastian atau sesuatu yang baru menjadi orang takut,” katanya.
Selain itu, ia memandang, stigma muncul dari informasi yang salah, serta rasa khawatir akan tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan keluarganya.
“Kemudian, rasa tidak percaya terhadap otoritas. Sebelum (pandemi) Covid-19, mereka didiskriminasi terhadap pelayanan kesehatan atau pendidikan, lalu terbawa dengan kondisi seperti ini,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Tim bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Urip Purwono menilai, stigma terhadap pasien Covid-19 sangat berbahaya. Hal itu memunculkan pandangan negatif, yang membuat mereka dijauhi.
“Dengan adanya stigma, secara psikologis ada kecenderungan bagi masyarakat umum untuk menyembunyikan risiko penyakit,” kata dia.
Menurut Irmansyah, yang harus dilakukan untuk melawan stigma adalah edukasi yang terus menerus. Informasi yang benar dan akurat, kata dia, mutlak harus dilakukan.
“Mereka (pasien) bukan hanya demam, batuk, dan sesak napas, tapi kondisi mentalnya juga terganggu,” katanya.
“Orang-orang ini membutuhkan dukungan, kalau malah dijauhi, mereka tambah berat kondisi mentalnya.”
Lebih lanjut, Irmansyah mengatakan, lingkungan paling utama memberikan dukungan. Ada beberapa contoh yang sudah dilakukan warga terhadap pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
“Dukungan bisa diberikan dengan mengirim makanan. Kalau dia tanpa gejala atau gejala ringan, kita bisa tunjukkan dukungan dengan mengirim ucapan yang positif dan perhatian. Itu akan sangat-sangat membantu,” ucapnya.
Sedangkan Nurul mengatakan, pihaknya melakukan pendampingan, membantu pasien Covid-19 agar terhubung dengan akses-akses pelayanan kesehatan yang sulit. Selain itu, pihaknya juga menghubungkan keluarga yang tengah berada di rumah sakit.
“Kalau orang tua di rumah sakit, siapa yang mengurus anaknya? Itu yang kami pikirkan,” kata dia.
Di sisi lain, Urip memaparkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melawan stigma terhadap orang dengan Covid-19. Pertama, menyebarluaskan fakta soal Covid-19. “Sangat mudah stereotip muncul, tanpa ada fakta yang benar,” ujar Urip.
Kedua, memanfaatkan jasa social influencer yang terlihat berinteraksi dengan kelompok yang terkena stigma. Ketiga, memperbesar dan menggaungkan suara mereka yang memiliki atau pernah mendapatkan pengalaman terkena Covid-19. Keempat, mengkomunikasikan pesan solidaritas dan komitmen bersama.
“Kelima, etika jurnalisme yang bertanggung jawab. Keenam, meluruskan mitos-mitos yang tidak benar, rumor-rumor yang beredar, dan mengoreksi bahasa-bahasa yang tidak benar,” kata Urip. (In-depth/features).