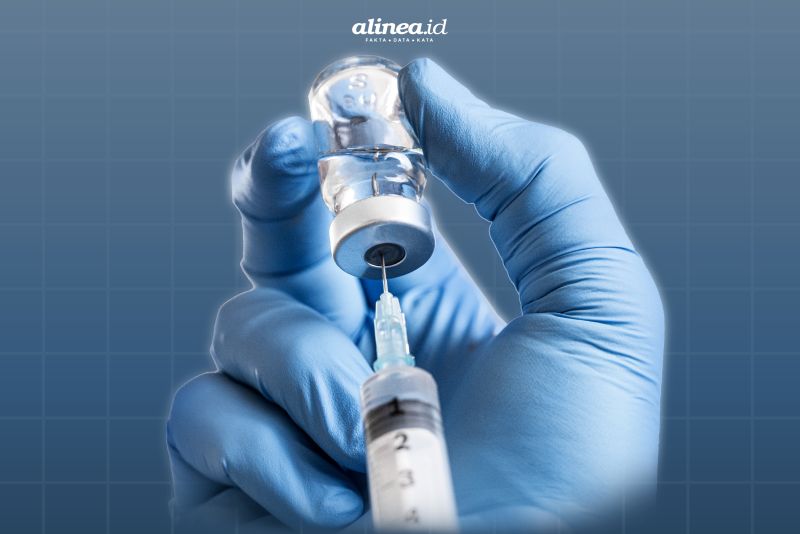Vaksinasi Covid-19: Belajar dari kegagalan masa lalu
Awal Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac tiba di Indonesia. Akhir Desember 2020, tiba tambahan sebanyak 1,8 juta dosis.
Indonesia juga akan mendatangkan vaksin buatan perusahaan farmasi dan biofarmasi asal Inggris, Astrazeneca dan perusahaan pengembang vaksin asal Amerika Serikat, Novavax. Selain itu, Indonesia juga berupaya menjalin kerja sama dengan perusahaan pembuat vaksin gabungan Amerika Serikat dan Jerman, Pfizer-Biontech.
Meskipun pemerintah tengah berupaya menyuntik vaksin secara massal tahun ini, tetapi tak semua warga bersedia divaksinasi. Hasil survei World Health Organization (WHO) terhadap 115.000 orang Indonesia pada September 2020 menunjukkan, 64,8% bersedia divaksin, 7,6% tidak bersedia, dan 27,6% ragu-ragu.
Lalu, survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dirilis Desember 2020 menyebut, hanya sebesar 56% responden yang percaya terhadap keamanan vaksin Covid-19. Sebesar 23% menyatakan tidak percaya. Sedangkan terkait efektivitas vaksin Covid-19 untuk membentuk imunitas tubuh, sebesar 55% responden percaya, 21% tidak percaya, dan sisanya tidak berpendapat.
Kegagalan vaksinasi
Dalam catatan sejarah, kegagalan vaksinasi memang pernah terjadi. Misalnya, kegagalan vaksinasi polio terhadap lebih dari 200.000 anak di lima negara bagian Amerika Serikat pada April 1955. Vaksin penyakit yang bisa melumpuhkan dan membunuh anak-anak itu dibuat oleh virolog Jonas Salk.
Menurut Direktur Pusat Pendidikan Vaksin Rumah Sakit Anak Philadelphia, Paul A. Offit dalam bukunya The Cutter Incident: How America’s First Polio Vaccine Led to the Growing Vaccine Crisis (2005), sekitar 40.000 anak malah demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, muntah, dan nyeri otot. Sebanyak 51 anak lumpuh dan lima anak meninggal dunia.
“Ini adalah salah satu bencana biologis terburuk dalam sejarah Amerika. Sebuah epidemi polio buatan manusia,” tulis Offit, seperti dilansir dari The Washington Post, 14 April 2020.
Michael Fitzpatrick dalam Journal of the Royal Society of Medicine edisi Maret 2006 menyebut, dalam beberapa hari usai divaksinasi, ada laporan kelumpuhan. Sebulan kemudian, program vaksinasi massal pertama untuk polio itu dibatalkan. Vaksin itu, sebut Fitzpatrick menyebabkan 40.000 kasus polio, kelumpuhan 200 anak, dan menewaskan 10 anak lainnya.
Sebelumnya, pada 30 Agustus 1954, seorang ilmuwan veteran di National Institutes of Health di Bethesda, Amerika Serikat Bernice R. Eddy memeriksa sampel vaksin dari Cutter Laboratories, Berkeley. Ia menemukan, vaksin yang dirancang untuk melindungi orang dari polio malah menyebabkan polio kepada monyet yang diuji coba. Alih-alih mengandung virus mati untuk menciptakan kekebalan buatan, sampel dari Cutter itu mengandung virus hidup dan menular.

Menurut The Washington Post, Bernice sudah memperingatkan hal itu. Namun, ratusan ribu anak-anak tetap mendapat suntikan vaksin Cutter.
Lalu, dugaan kegagalan vaksin campak mengemuka pada 1998. Mulanya, pada 1996 seorang pengacara Inggris Richard Barr mencari saksi ahli untuk gugatan class action yang menuduh kegagalan vaksin campak pada anak-anak. Ia menghubungi mantan dokter Inggris, Andrew Wakefield.
Kemudian, dilansir dari Interesting Engineering edisi 19 Desember 2020, pada 1998 Wakefield dan beberapa koleganya menerbitkan makalah di jurnal medis Inggris, The Lancet. Intinya menyatakan, ada hubungan antara vaksin measles, mumps, and rubella (MMR) dengan autisme.
Akibatnya, terjadi penurunan tajam vaksinasi, yang berimbas peningkatan kasus campak dan gondongan. Padahal, pada 1990, dengan vaksinasi MMR angka kematian akibat campak pada 1980 yang sebesar 2,6 juta turun menjadi 454.000 pada 1990.
Masih dilansir dari Interesting Engineering, hasil investigasi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, American Academy of Pediatrics, dan National Health Service Inggris tak menemukan bukti hubungan antara vaksin MMR dan autisme.
“Investigasi menemukan bahwa Wakefield telah memanipulasi data dan bukti, dan memiliki konflik kepentingan yang jelas. Pada 2004, artikel Wakefield telah dihapus dari The Lancet, dan pada 2010 jurnal itu mencabut artikel tersebut,” tulis Marcia Wendorf di Interesting Engineering.
Belajar dari cacar
Indonesia pernah mendapat pelajaran berharga dari vaksinasi cacar. Menurut WHO, seperti dikutip dari Medical News Today edisi 30 November 2020, cacar yang disebabkan infeksi virus Variola merupakan salah satu penyakit paling menghancurkan dalam sejarah umat manusia. Selama kira-kira 3.000 tahun, penyakit menular ini membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Sepanjang abad ke-20, cacar menewaskan 300 juta orang di dunia.
Penyakit cacar dipercaya masuk pertama kali ke wilayah Jawa, tepatnya Batavia, pada 1644. Pada abad selanjutnya, penyakit ini menular ke beberapa wilayah lain di Jawa dan luar Jawa.
Menurut staf pengajar jurusan sejarah Unviersitas Gadjah Mada (UGM) Baha’Uddin dalam tulisannya “Dari Mantri hingga Dokter Jawa: Studi Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Penanganan Penyakit Cacar di Jawa Abad XIX-XX”, terbit di jurnal Humaniora edisi Oktober 2006, pada 1781 lebih dari 100 orang terkena cacar di Batavia, 20 di antaranya meninggal dunia.
Baha’Uddin menyebut, saat pemerintahan Inggris di Jawa (1811-1816) diketahui 1.019 bayi yang lahir di Jawa, 102 di antaranya mati karena cacar. Artinya, tingkat mortalitas karena cacar terhadap anak-anak mencapai 10%. Lalu, antara 1775-1815, cacar sudah menular ke beberapa kota besar di Jawa.
Upaya preventif dilakukan pada 1779 oleh seorang dokter Belanda, J. van der Steege. Ia melakukan uji coba variolasi di Batavia. Hingga 1781, ia melakukan variolasi terdapat 100 penderita cacar di Batavia. Namun, tindakan itu mengakibatkan seorang anak meninggal dunia.
Dilansir dari National Interest, 1 Agustus 2020, seorang dokter Inggris bernama Edward Jenner menemukan vaksin cacar pertama pada 1796. Ia melakukan percobaan menyuntik seorang anak dengan bahan yang didapat dari lesi pada ambing sapi yang terinfeksi cacar sapi. Bocah itu pun terbukti kebal cacar.
Dengan ditemukan vaksin ini, pemerintah kolonial berinisiatif mendatangkannya. Vaksin pertama tiba di Batavia pada Juni 1804. Pada awal abad ke-19, vaksinasi cacar mulai dilakukan. Pengiriman di periode selanjutnya terus dilakukan untuk mengatasi wabah cacar.
Menurut Baha’Uddin, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di masa itu mendorong pemerintah kolonial melatih orang pribumi untuk menjadi mantri cacar. Mereka bertugas sebagai penyuntik vaksin di sejumlah daerah.
Akan tetapi, Baha’Uddin menyebut, terjadi kegagalan vaksinasi pada paruh pertama abad ke-19. Ada beberapa faktor yang menjadi biang keladinya. Pertama, buruknya kualitas vaksin. Kedua, pengetahuan mantri cacar yang minim.
“Dalam beberapa kejadian, mantri cacar sering melakukan kesalahan dengan menyuntik orang yang kulitnya masih terluka atau orang yang sudah terjangkiti, tetapi bisulnya belum timbul,” tulis Baha’Uddin.
“Akibatnya, antara 10-15% vaksinasi yang dilakukan mengalami kegagalan.”
Faktor irasional dari penduduk juga menjadi penyebab vaksinasi gagal. Baha’Uddin menulis, pada 1831 para orang tua di Madiun tak bersedia mengantar anaknya divaksinasi karena beredar kabar tujuan pengumpulan anak-anak hanyalah akal-akalan residen. Mereka percaya, tujuan pengumpulan anak-anak itu untuk dijadikan makanan buaya peliharaan Residen Madiun.
Lalu, pejabat pemerintah lokal dan para ulama juga menentang vaksinasi karena dianggap sebagai penolakan terhadap takdir. Alasan lainnya, penduduk belum percaya manfaat vaksin karena kerap terjadi anak-anak yang sudah divaksinasi masih tertular cacar.
Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia terus berupaya memberantas cacar. Di dalam buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia (2007) disebutkan, pemerintah mengambil kebijakan peningkatan pengamatan dan pemberian kekebalan penyakit cacar kepada sepertiga penduduk. Pemerintah juga mengambil kebijakan lain, dengan ikut serta dalam Global Smallpox Eradication Program (SEP) pada 1967. Sejak ikut dalam SEP, Indonesia mulai mengalami banyak kemajuan dala pemberantasan penyakit cacar, hingga dinyatakan bebas cacar oleh WHO pada 25 April 1974.

Kesiapan vaksin Covid-19
Terkait vaksinasi Covid-19, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana vaksinasi massal masih menunggu emergency use authorization (EUA) atau penggunaan dalam keadaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nadia menyebut, UEA tetap keluar sesuai jadwal, yakni pada minggu kedua atau ketiga Januari 2021.
"Tentunya persiapan-persiapan, seperti data sasaran, tenaga pelaksananya, vaksinatornya, sudah kita lakukan pelatihan,” kata Nadia ketika dihubungi reporter Alinea.id, Minggu (3/1).
“Juga untuk sarana-prasarana sudah kita siapkan untuk bagaimana mengelola distribusi logisitik vaksin."
Nadia menyebut, pemerintah tetap optimis vaksinasi Covid-19 tak bermasalah. Sebab, vaksin yang didatangkan ke Indonesia adalah hasil rekomendasi WHO.
"Kalau kemarin kan Pfizer sudah mendapat UEA dari WHO, nanti juga vaksin-vaksin lain kalau sudah menyelesaikan uji klinis tahap tiga, pasti juga mendapatkan rekomendasi WHO," ujarnya.
Sementara itu, dokter ahli vaksin sekaligus CEO inHarmony Clinic, Kristoforus Hendra Djaya mengatakan bahwa kecil kemungkinan risiko yang ditimbulkan dari vaksin buatan Sinovac. Alasannya, vaksin buatan Sinovac adalah tipe inaktif (sudah tidak ada yang hidup), yang selama ini sudah banyak digunakan di berbagai vaksin. Bahkan, kata dia, Bio Farma sendiri memiliki teknologi untuk memprosesnya.
Menurut dia, berdasarkan banyak riset dan pengalaman, vaksin inaktif tak terlalu berisiko. Sebagian besar reaksi simpang yang mungkin muncul adalah reaksi lokal dari penyuntikan.
“Biasanya cukup ringan,” kata dia saat dihubungi, Minggu (3/1).
“Umumnya demam dan pusing. Namun, ini bukan keluhan yang dominan dan biasanya ringan dan singkat, serta tidak berbahaya.”
Kristoforus mengatakan, kegagalan vaksin di masa lalu, lazimnya akibat kesalahan produksi atau human error. Virus hidup masuk ke dalam vaksin yang seharusnya mengandung hanya virus inaktif. Hal itu kemungkinan besar terjadi dengan kondisi teknologi di masa lalu. Ia memastikan, saat ini kesalahan produksi sangat kecil terjadi karena ada pengawasan yang ketat.
"Walaupun vaksinnya baru dan dipercepat sekalipun, berbagai pihak mengawasi dan semua mata memandang, sehingga perusahaan produsen vaksin seharusnya tidak bisa berbuat sembarangan dan memproduksi barang yang sub-standard," ujar dia.
Meski begitu, Kristoforus berharap pemerintah tetap menjalankan vaksinasi sesuai waktu yang disepakati. Ia menekankan, menjelang vaksinasi, persiapan pelaksanaannya terpaksa berjalan paralel dengan risetnya. Sehingga, saat riset dirilis, vaksin sudah siap didistribusikan.
Menurut Kristoforus, hal itu dilakukan di seluruh dunia, dengan sedikit asumsi dan spekulasi, yang mau tidak mau harus dilakukan untuk mempercepat pemulihan krisis global akibat pandemi.
"Kalau habis penelitian baru mengimpor vaksinnya, bisa jadi program vaksinasi akan mundur berbulan-bulan dan banyak yang menderita,” katanya.
“Jika pemerintah cukup bijak, maka pemerintah seharusnya tetap mengeksekusi vaksinasi setelah EUA keluar."