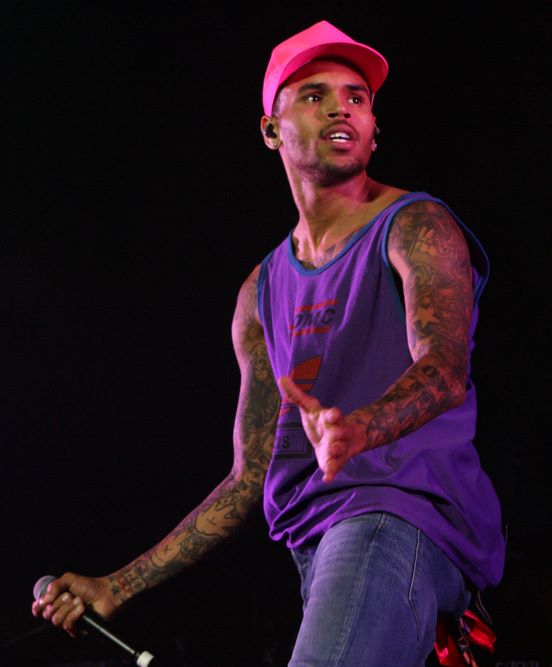Foto Tara Basro: Bias antara pornografi dan kampanye body positivity
Aktris Andi Mutiara Pertiwi Basro, atau lebih dikenal dengan nama Tara Basro, beberapa waktu lalu menjadi perbincangan warganet. Di Twitter, perempuan berusia 29 tahun itu sempat mengunggah foto yang berani: tanpa busana, dalam pose duduk miring dan menutup bagian intim tubuhnya. Selain foto itu, di Instagram ia mengunggah foto hitam-putih, berbikini, memperlihatkan ketidaksempurnaan bagian perutnya.
Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sempat menganggap foto Tara Basro di Twitter melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Foto itu dianggap mengandung unsur pornografi.
Karena mengundang polemik, Tara akhirnya menghapus fotonya di Twitter, tetapi tidak yang di Instagram. Seakan-akan plintat-plintut, selang beberapa hari, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate angkat bicara. Ia membantah foto itu melanggar UU ITE.
Sempat ramai karena dituding melanggar UU ITE, tak sedikit warganet yang membela Tara Basro. Bahkan, tagar #TaraBasro sempat populer di Twitter. Mereka menganggap, apa yang dilakukan Tara adalah kampanye tentang tubuh positif (body positivity).
Ketika dikonfirmasi terkait foto Tara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo Fernandus Setu enggan memberikan komentar lebih jauh.
“Silakan dengan Pak Menteri,” ujar Ferdinandus saat dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (10/3).
Putu Ayu Serly Wulandari adalah salah seorang warganet yang mendukung Tara Basro. Sebagai ungkapan membela pemeran utama film Perempuan Tanah Jahanam (2019) itu, ia mengunggah foto lama, lengkap merinci berat badannya saat itu.
Menurut Ayu, kecantikan perempuan bukan hanya dilihat dari tubuhnya, tetapi juga mempertimbangkan hal lain, seperti prestasi. Ia percaya, bagaimana pun bentuk tubuhnya, semua perempuan pada dasarnya cantik.
“Dulu saya itu kurus banget, baru masuk kuliah saja mulai berisi. Saat kurus, sering di-bully. Tapi saya enggak peduli omongan orang,” ujar Ayu saat dihubungi, Senin (9/3).
Ayu pun sadar, apa yang dilakukan Tara Basro adalah kampanye body positivity. Ia mengatakan, ikut menyuarakan body positivity karena banyak perempuan yang dikenalnya kurang percaya diri, setelah menerima penilaian orang tentang bentuk fisik mereka.

Ketelanjangan dan gerakan sosial
“Dari dulu yang selalu gue denger dari orang adalah hal jelek tentang tubuh mereka, akhirnya gue pun terbiasa ngelakuin hal yang sama, mengkritik dan menjelek-jelekan. Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki. Setelah perjalanan yang panjang, gue bisa bilang kalau gue cinta sama tubuh gue dan gue bangga akan itu. Let yourself bloom,” tulis Tara Basro dalam deskripsi fotonya di Instagram, yang diunggah sepekan lalu.
Deskripsi foto itu semakin menyiratkan tujuan Tara mengunggah foto, yakni kampanye body positivity. Body positivity merupakan gerakan sosial berlandaskan keyakinan semua orang mesti punya citra tubuh positif, menentang cara publik melihat gambaran tubuh ideal.
Pada 1850-an hingga 1890-an, perempuan di Amerika Serikat dan Inggris melawan standar sosial yang melihat perempuan ideal adalah mereka yang memiliki pinggang kecil. Gerakan yang dinamakan Victorian Dress Reform itu diakui sebagai awal dari gelombang feminisme dan kampanye body positivity.
Menurut Laura Darnell dalam tulisannya “An Introduction to Feminism and Cross-Cultural Body Image in the United States”, istilah body positivity merujuk nama organisasi yang membantu menyembuhkan orang-orang dari tekanan sosial akibat bentuk tubuhnya, Body Positive.
Organisasi itu didirikan Elizabeth Scott dan Connie Sobczak pada 1996 di Amerika Serikat. Lantas, organisasi tersebut menginspirasi gerakan body positivity di media sosial dan situs web. Ada tiga gerakan body positivity yang populer di jagat maya, yakni #HereIAm, #LessisMore, dan #ImNoAngel.
Alexandra Sastre dalam buku Toward a Radical Body Positive: Reading the Online Body Positive Movement (2016) menulis, visibilitas body positivity di era digital sudah berkembang, bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebuah praktik yang bisa dilacak dari serangkaian kiasan visual dan retorik tersendiri.
Sastre menulis, memahami body positivity tergantung penyaringan pesannya, pemeriksaan bagaimana pesan itu dipraktikkan, serta bagaimana body positivity tersebut dilakukan melalui kalimat dan gambar dalam ruang media digital.
Konsep body positivity menekankan penggabungan fotografi sebagai saluran keberadaan tubuh, dengan visibilitas dan cinta diri sebagai tujuan akhir.
Ketelanjangan tubuh dan menampilkan bagian yang tak sempurna, tulis Sastre, merupakan penanda ganda. Hal itu dianggap sebagai contoh yang diharapkan bisa meruntuhkan konsep tubuh ideal, hasil pencitraan rekayasa.
“Dengan kata lain, pakaian, make up, dan perlengkapan lain, dipahami sebagai penyumbat kontur tubuh sebenarnya. Pada gilirannya, gambar tubuh telanjang atau setengah telanjang dipahami untuk menyampaikan keaslian,” tulis Sastre dalam bukunya.
Di Indonesia, standar kecantikan erat kaitannya dengan obsesi memiliki kulit putih. Di dalam bukunya Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional (2017), L. Ayu Saraswati menulis, obsesi pada kulit putih dapat dilacak dari karya Ramayana, yang mendeskripsikan perempuan cantik bila berkulit terang serupa cahaya bulan.
Kolonialisme lantas mengukuhkan citra perempuan cantik berkulit putih untuk superioritas ras Kaukasia. Saat pendudukan Jepang, konsep perempuan ideal berubah dari kulit putih Eropa menjadi putih orang Jepang. Hingga kini, obsesi berkulit putih masih digembar-gemborkan berbagai iklan produk kecantikan.

Tergesa-gesa menilai dan tabunya tubuh
Menurut Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto, Kemenkominfo terlalu tergesa-gesa menghakimi kampanye body positivity yang dilakukan Tara Basro, tanpa memahami konteksnya.
Ia mengatakan, sebuah unggahan foto tidak berdiri sendiri dan tidak hadir dari ruang kosong. Bila diperhatikan, kata dia, sesungguhnya unggahan foto Tara saling terkait dengan unggahan sebelum dan setelahnya.
Damar mengungkapkan, Tara bukan sedang menjual diri untuk pornografi atau mempertontonkan hal-hal yang menimbulkan berahi. Sehingga, tidak layak untuk dicap sebagai tindakan melanggar hukum.
“Yang perlu disayangkan (pernyataan) ini keluar dari mulut pejabat publik, dikutip media dan menimbulkan semacam keresahan,” ujar Damar saat dihubungi, Senin (9/3).
Damar pun mengkritik penggunaan Pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang pelanggaran kesusilaan. Baginya, pasal itu membungkam gerakan perempuan dalam memperjuangkan haknya.
Tafsir Pasal 27 ayat 1 UU ITE, menurut Damar, juga menimbulkan ketidakjelasan hukum karena cakupannya meluas ke ranah yang seharusnya diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Penyanyi dari grup musik Tika and The Dissidents sekaligus aktivis kesetaraan gender Kartika Jahja pun mengampanyekan body positivity, yang ia beri nama “Tubuhku Otoritasku”.
Nama itu berawal dari sebuah lagu yang ia tulis pada 2013. Menurutnya, kampanye body positivity itu sudah menjadi proyek kolaborasi berbentuk video pada 2016. Tujuannya, untuk menyerukan solidaritas kepada perempuan, terutama hak atas tubuh.
“Bahwa tubuhnya adalah miliknya, bukan objek yang bisa dimiliki dan diatur orang lain. Hanya si pemilik tubuh lah yang menentukan apa itu cantik,” ujar Tika, sapaan akrabnya, saat dihubungi, Rabu (11/3).
Tika menuturkan, kampanye body positivity muncul untuk mengembalikan perempuan menjadi subjek atas tubuhnya. Menurut dia, gerakan body positivity mengusung gagasan positif untuk menggeser cara pandang terhadap tubuh yang selama ini negatif, seperti tabu, kotor, aib, kurang gemuk, kurang kurus, hingga kurang putih.
Lebih lanjut, ia mengatakan, isu body positivity akan menjadi kontroversial jika perempuan yang menggaungkannya tumbuh dalam masyarakat misoginis—memandang perempuan sekadar objek.
“Pernyataan seorang perempuan untuk memberdayakan tubuhnya sendiri sesungguhnya sama sekali bukanlah hal kontroversial,” katanya.
Menurutnya, ekspresi body positivity tergantung perempuan sebagai pemegang otoritas tubuhnya dan pernyataan apa yang disampaikan. Jika menilik kampanye-kampanye body positivity secara global, ekspresinya sangat beragam.
Dari perempuan yang memilih membuat pernyataannya dengan memperlihatkan lebih banyak kulit atau justru menutupnya. Ada pula perempuan yang menyoroti ukuran tubuh, hak reproduksi, warna kulit, hingga disabilitas.
“Semua pesannya kurang lebih terkait menerima dan mencintai keragaman tubuh. Mereklamasi hak untuk membuat keputusan atas tubuh kita sendiri,” ucapnya.
Sementara itu, penulis buku C*abul: Perbincangan Serius tentang Seksualitas Kontemporer (2019) Hendri Yulius menilai, istilah pornografi masih diperdebatkan dan tidak selalu terkait dengan ketelanjangan. Ia mengatakan, indikator pornografi biasanya ketelanjangan atau aktivitas seksual yang bertujuan merangsang berahi.
Hendri memandang, terlalu berlebihan menganggap kampanye body positivity sebagai wujud pornografi. Sebab, penilaian terhadap ketelanjangan masing-masing orang berbeda.
Ia mengatakan, saat berpegang dengan definisi pornografi sebagai ketelanjangan untuk merangsang berahi pun, masih terbentur dengan keterbatasan. Menurut dia, apa yang merangsang berahi, masing-masing orang punya pandangan berbeda.
“Untuk kasus Tara Basro memang tidak untuk menampilkan ketelanjangan, bukan untuk merangsang berahi karena niatnya kampanye body positivity, supaya orang lebih percaya diri dengan tubuhnya dalam bentuk dan kulit apa pun,” ujar Hendri saat dihubungi, Senin (9/3).
Hendri justru mengapresiasi usaha Tara Basro untuk menyuarakan body positivity, yang akhirnya mendorong warganet melakukan hal serupa. Kapasitas Tara, yang merupakan seorang selebritas dan ikon industri hiburan memicu warganet mendukungnya.

Namun, sebaliknya ia melihat, kampanye body positivity akan memicu perlakuan tak menyenangkan bila dilakukan orang bertubuh gemuk yang tidak terkenal. Ia mengingatkan untuk tidak melupakan orang bertubuh gemuk, yang posisinya bukan selebritas, sehingga tidak menerima pembelaan sebesar Tara Basro. Hendri khawatir, jika mereka meniru Tara, bukannya apresiasi warganet yang didapat, malah hujatan.
“Jadi, ini bias-bias yang mungkin harus kita lihat juga dari model kampanye Tara Basro. Ini yang kita perlu aware atas perbedaan status sosial, kelas sosial, dan privasi seseorang,” ucapnya.
Ujung-ujungnya, ungkap Hendri, kampanye body positivity Tara hanya untuk memperlihatkan status selebritasnya, menunjukkan seberapa modern dan liberalnya para publik figur.
Menurut Hendri, pergeseran nilai dan perubahan budaya masyarakat di era digital, yang memunculkan keterbukaan informasi, menyebabkan batasan privasi menjadi abu-abu. Dunia maya, kata dia, meleburkan definisi privasi dan publik—yang terkait kampanye body positivity Tara Basro—bisa menimbulkan polemik.
“Yang kemudian jadi masalah ialah dia (Tara Basro) menggunakan tubuhnya sendiri. Sesuatu yang dianggap privasi, dianggap tabu di Indonesia untuk memperlihatkan tubuh,” tutur Hendri.