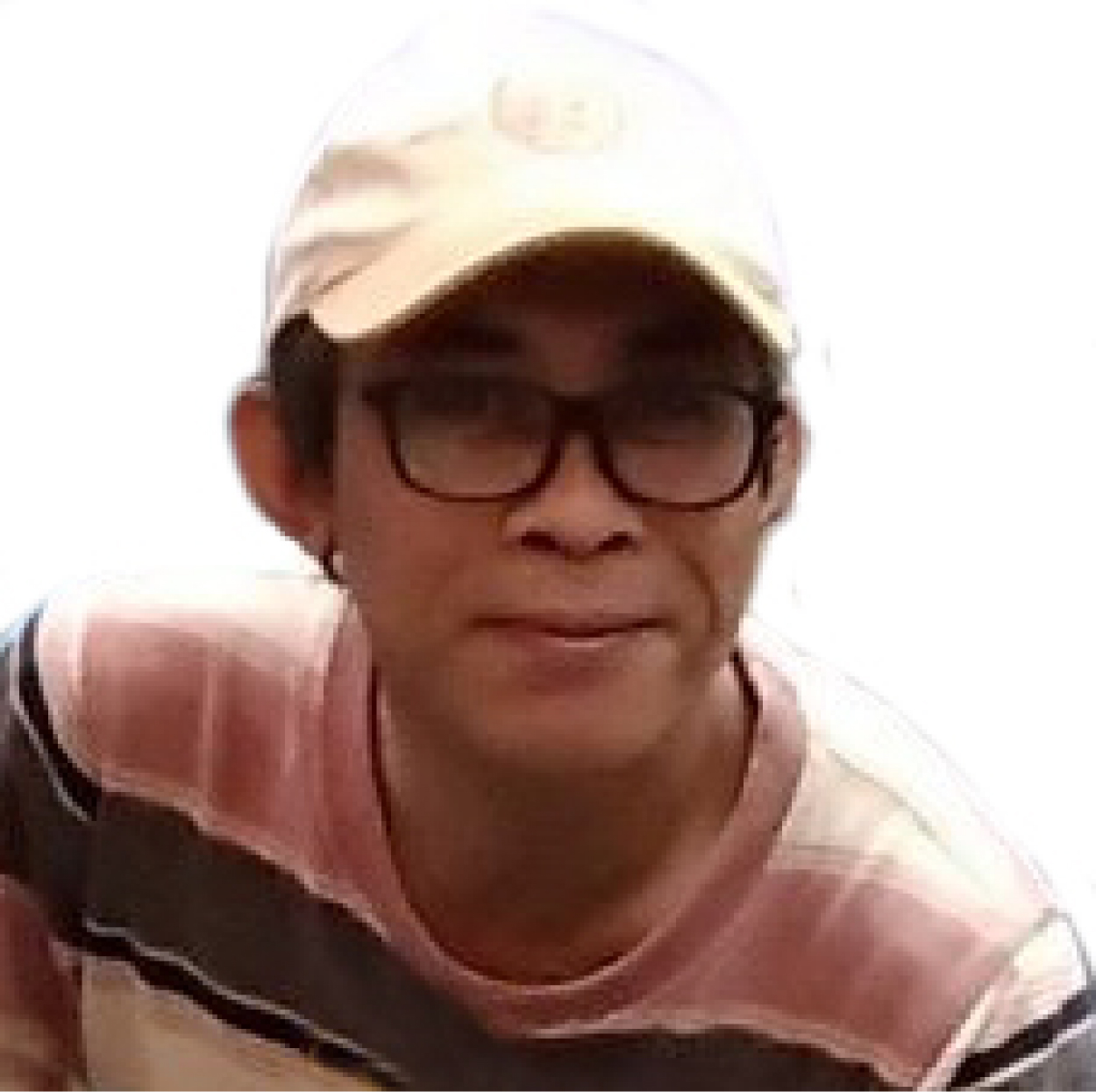Bencana di media, media di bencana
Bencana dalam bentuk apapun mulai dari perang, penyakit menular seperti Covid-19, kelaparan, krisis iklim, dan lainnya selalu memiliki dimensi yang penting bagi media. Karena nilai beritanya sangat tinggi. Biasanya diukur seberapa skalanya. Semakin besar dampaknya, makin banyak korban, itu dianggap semakin tinggi nilai beritanya.
Perhatian publik dan keingintahuan tentang peristiwa itu umumnya sangat tinggi. Satu hal, terutama bencana yang berdampak pada orang, semakin besar dampaknya dan semakin dekat dengan kita, misalnya terjadi di kampung kita atau di provinsi di negara kita, maka ketertarikan publik terhadap itu semakin tinggi. Itu yang membuat media berbondong-bondong memberitakan mengenai bencana.
Ahmad Arif, Ketua Umum Jurnalis Bencana, memaparkan pandangan tersebut dalam diskusi online DMC Dompet Dhuafa, Jumat (18/2/2022). Berbagi ilmu tentang dunia jurnalistik kebencanaan, Arif mengungkai 'Dimensi Manusia dalam Bencana dan Peran Jurnalisme' sebagai pokok bahasan. Diuraikannya, yang menjadi problem di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak kritik bagaimana praktik pemberitaan bencana di media massa yang diangkat sering kali tidak etis.
"Beberapa tahun lalu, misalnya, pemberitaan di salah satu televisi saat kecelakaan pesawat Air Asia memotret proses evakuasi korban dari laut. Tayangan itu dianggap terlalu sadis. Jadi dramatisasi yang dianggap berlebihan, sehingga dikhawatirkan berdampak psikologi yang buruk pada keluarga korban dan anak-anak. Kalau diingat, tayangan televisi itu bisa dilihat oleh siapa saja sehingga seorang pekerja media perlu memperhitungkannya," katanya.
Menurut Arif, banyak kejadian serupa, contohnya letusan Gunung Merapi pada 2010. Sampai-sampai masyarakat di lokasi bencana sempat melarang televisi masuk kampung mereka karena dianggap justru akan memicu kekacauan. Di luar itu banyak sekali kritik yang dialamatkan kepada media. Secara umum, yang disoroti salah satunya seolah-olah 'bad news is good news'. Bila makin dramatis tambah banyak korban, semakin menarik untuk dieksploitasi. Terkadang gambar mayat, orang yang menangis, kemudian diperbesar tanpa memperhitungkan bagaimana dampak pada pemirsa. Ini sering kali jadi kritik terhadap pemberitaan media di Indonesia.
"Saya kebetulan meliput tsunami Aceh pada 2004, hampir tiga tahun di sana. Kemudian menulis buku 'Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme'. Ini sebenarnya sebagai otokritik bagaimana media di Indonesia dalam praktik pemberitaan bencana itu masih banyak sekali hal yang harus dikoreksi," ujarnya.
Setidaknya Arif menemukan tiga hal di palagan yang diterjuninya. Pertama, ada ketidaktahuan. Peliputan bencana itu jadi salah satu liputan yang paling rumit dalam praktik jurnalisme. Di situ menjadi penting seorang jurnalis harus dibekali mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana berinteraksi dengan sumber, mana yang boleh diberitakan dan mana yang tidak boleh.
"Sayangnya, jurnalis yang dikirim ke daerah bencana itu terkadang jurnalis baru yang tidak memiliki pengetahuan. Sebenarnya boleh saja jurnalis baru, tapi sebaiknya ada jurnalis senior yang mendampinginya. Itu sebagai medium untuk transfer pengetahuan. Di Indonesia, beberapa media sudah membekali jurnalis mereka. Ada wartawan-wartawan spesialis yang disiapkan untuk meliput bencana, tapi mayoritas memang tidak (memiliki bekal) sehingga pengetahuan menjadi tantangan bagi peliputan," cetus Arif.
Katanya, pengetahuan mengenai etik juga diperlukan. Dalam liputan bencana, dampak efek psikologis, trauma, sangat kental. Ini diperlukan, tapi jarang sekali dipahamkan kepada jurnalis, selain juga ada persoalan ekonomi-politik, misalnya, dalam tren menguatnya clickbait. Judul-judul yang sensasional untuk mengincar orang biar mengklik dan mengabaikan substansi, malah justru menambah parah liputan bencana.
Arif menyebutkan, selama ini bencana sering dilihat oleh media di Indonesia dan mungkin juga oleh masyarakat secara umum, sebagai satu kejadian saja. Satu event, hanya seperti itu. Sebenarnya bencana itu satu siklus, yang bukan hanya saat kejadian, justru dimensi yang sangat penting di mana media massa bisa berperan adalah fase sebelum bencana dan setelah bencana.
"Sebelum bencana, media sangat penting dalam memberikan peringatan informatif mengenai kerentanan di suatu wilayah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam memitigasi bencana itu, mengurangi risiko, kerugian material dan jiwa. Dimensi ini yang menurut saya masih kurang sekali dilakukan oleh media. Media di Indonesia, kalau dibandingkan dengan di Jepang, jauh lebih fokus pada saat bencana," sambungnya.
Dijelaskannya, saat bencana itu news value tinggi dan sering kali tidak lebih susah meliput bencana sebelum kejadian dan setelahnya. Padahal setelah kejadian juga momen yang sangat penting di mana bisa dikawal proses rekonstruksi, rehabilitasi, dan apa yang dipelajari dari bencana tersebut. Itu bisa ditransformasikan untuk menghadapi bencana berikutnya. Itu peran penting media, menurut Arif wartawan senior Kompas.
Bukan hanya jurnalis saja atau pemangku kepentingan dari pemerintah yang perlu mengetahui soal bencana, tapi akar rumput masyarakat yang pertama kali perlu mengetahuinya. Apalagi banyak kelompok masyarakat yang membentuk grup relawan untuk mengatasi bencana. Karena pertolongan pertama adalah kepada orang yang berada di lokasi. Soal penting itu diungkapkan Adek Berry, fotografer profesional.
Peran fotografi dalam menyuarakan hak penyintas bencana dijabarkan Adek dalam situasi. "Kalau kita berada di lapangan, dampak bencana itu bukan hanya kepada manusia tetapi juga hewan ternak dan alam sekitar di mana bencana terjadi. Tren risiko dalam liputan bencana itu sangat besar, kita sebut 'red zone', di mana kita memasuki tempat yang tidak biasa. Seperti di Indonesia ada gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan banjir," tuturnya.
Penulis buku 'Mata Lensa' menwanti-wanti perlunya persiapan bagi jurnalis, bukan hanya jurnalis, tapi semua orang yang akan masuk ke wilayah bencana tersebut apakah sukarelawan dan pemberi bantuan. "Jadi jangan sampai masuk ke lokasi bencana, malah terkena bencana," pesannya.