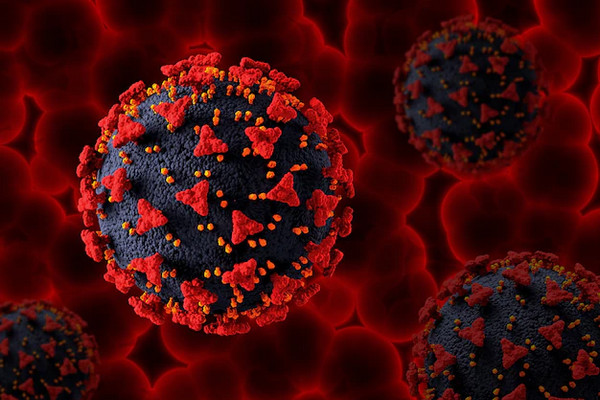TRIPS dan mimpi vaksin murah negara-negara 'papa'
Sebuah proposal "berani" diajukan India dan Afrika Selatan ke The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Properti (TRIPS) Council di markas World Trade Organization (WTO), Jenewa, Swiss, awal Oktober 2020. Dalam proposal itu, India dan Afrika Selatan meminta agar kepatuhan terhadap regulasi TRIPS diabaikan dalam proses pengadaan vaksin Covid-19 atau TRIPS waiver.
Tak butuh lama, proposal itu segera mendapat dukungan dari berbagai negara berkembang dan negara-negara "papa". Dalam proposal baru bernomor IP/C/W/669.Add.3, Kenya, Mozambique, Swaziland, dan Pakistan turut bergabung sebagai inisiator bersama India dan Afrika Selatan.
Pada umumnya, keenam negara itu mendesak agar kewajiban memberikan hak kekayaan intelektual, paten, desain industrial, dan perlindungan terhadap informasi perdagangan rahasia yang diatur dalam TRIPS diabaikan selama pandemi. Regulasi itu dinilai mempersulit akses negara miskin untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin, obat-obatan, serta peralatan medis untuk menangani pandemi.
Proposal itu bersifat opsional. Artinya, negara-negara yang terikat kesepakatan TRIPS boleh memilih mengabaikan ketentuan perlindungan intelektual properti dalam TRIPS atau tetap mematuhinya saat membeli atau memproduksi vaksin Covid-19.
Di pertemuan informal TRIPS Council pada November 2020, inisiatif tersebut dibahas. Perdebatan antara negara pendukung dan negara penolak proposal berlangsung keras. Penolakan terutama datang dari negara-negara maju semisal Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Uni Eropa juga menolak proposal itu.
Perdebatan panjang kembali mengemuka dalam pertemuan-pertemuan informal TRIPS jelang sidang Majelis Umum WTO pada 16-17 Desember. Kesepakatan kembali tidak tercapai. AS dan negara-negara penolak beranggapan TRIPS waiver tidak adil bagi perusahaan dan bisa mengganggu perkembangan riset teknologi vaksin.
Sebagai bagian dari bentuk penolakan, Kanada dan beberapa negara di Eropa mengusulkan janji untuk mendonasikan kelebihan vaksin yang mereka miliki ke fasilitas COVAX, lembaga bentukan World Health Organization (WHO) dan sejumlah negara yang ditugasi memburu obat-obatan dan vaksin Covid-19 bagi negara anggota mereka.
Solusi lainnya ditawarkan dalam bentuk penggunaan klausul TRIPS flexibilities. Dalam klausul itu, negara-negara anggota WTO diperkenankan mengajukan dispensasi-dispensasi khusus untuk mengabaikan kewajiban perlindungan intelektual properti suatu produk jika hal itu diperlukan dalam keadaan darurat.
Namun demikian, solusi itu ditolak perwakilan Afrika Selatan, Mustaqeem Da Gama. Menurut Da Gama, fleksibilitas pada aturan TRIPS hanya kerap berlaku kasuistik. Di sisi lain, pandemi Covid-19 butuh respons secara global.
"Sejak kesepakatan TRIPS berlaku, negara-negara berkembang terus mengalami tekanan dari mitra dagang untuk membatasi penggunaan flexibilities," kata Da Gama sebagaimana disitat dari situs Third World Network.
Di lain sisi, AS tetap pada pendiriannya. AS menganggap tak semua negara memiliki kemampuan dan teknologi untuk memproduksi obat-obatan, peralatan medis, dan vaksin Covid-19. Delegasi Negeri Paman Sam juga bersikukuh pengabaian terhadap regulasi TRIPS bakal jadi preseden buruk yang menghambat perkembangan penemuan-penemuan medis di masa depan.
Karena tidak menemui titik temu, WTO menunda keputusan mengenai proposal tersebut. WTO meminta negara-negara anggota TRIPS kembali melanjutkan pembahasan pada Maret 2021.
Di luar WTO, upaya memperjuangkan pengabaian TRIPS juga digelar beragam lembaga swadaya masyarakat (LSM) global, semisal Oxfam, Health Action International, Médecins Sans Frontières (MSFs). Sejak tahun lalu, MSFs bahkan rutin berkampanye untuk mendesak negara-negara di dunia untuk mendahulukan "nyawa ketimbang keuntungan".
"Pandemi global bahkan tidak akan mampu menghentikan perusahaan farmasi mengikuti pendekatan bussiness as usual mereka. Jadi, negara-negara harus menggunakan segala cara untuk memastikan produk-produk medis untuk mengobati Covid-19 murah dan mudah diakses," kata Sidney Wong, executive co-director MSF Acces Campaign.

Antara profit dan nyawa
Kepada Alinea.id, peneliti bidang etika kesehatan publik di University of Birmingham, Inggris, Citta Widagdo mengatakan, inisiatif India dan Afrika Selatan perlu didukung. Ia berpandangan pemberlakuan hak paten produk medis tidak tepat diterapkan saat pandemi.
"Perlu diingat bahwa harga obat dan vaksin naik jika pemegang paten memutuskan untuk menghargai akses dan lisensi dengan harga tinggi. Perlindungan rahasia dagang juga dapat membatasi produksi dan distribusi inovasi vaksin," ujar Citta saat dihubungi, Selasa (12/1) lalu.
Dengan pemberlakuan TRIPS waiver, menurut Citta, transfer teknologi untuk memproduksi obat-obatan dan vaksin bisa merata. Harga vaksin pun bisa ditekan semurah mungkin karena diproduksi perusahaan farmasi lokal tidak terbebani oleh royalti.
"Pengembangan vaksin dan obat bisa jadi lebih cepat karena bisa dimanufaktur oleh berbagai multiple actors dan tidak hanya terkonsentrasi di tangan patent holder besar. Jadi, dunia tergantung pada fasilitas manufaktur yang sama," ujar Citta.
Citta juga tidak sepakat jika solusi aksesibilitas dan harga vaksin tergantung sepenuhnya pada hasil dari proses negosiasi antara perusahaan farmasi dan negara-negara yang membutuhkan. Menurut dia, negosiasi semacam itu biasanya berjalan lamban.
"Sementara kalau mau negosiasi harga vaksin, supaya royaltinya dikurangi, ya, harus case per case, country by country. Jadi, prosesnya panjang dan lama. Negara-negara yang tidak punya power dan uang, ya, tidak bisa negosiasi paten ini," ucap Citta.
Berkaca pada kasus-kasus di masa lalu, Citta mengatakan, regulasi TRIPS terkait paten produk medis kerap menimbulkan persoalan. Ia mencontohkan terhentinya pengembangan vaksin pneumonia pneumococcal conjugate vaccine (PCV-13) di Korea Selatan karena diblok oleh Pfizer sebagai pemegang paten.
Perkara serupa juga terjadi antara Pfizer dengan perusahaan obat India, Indian Vaccine Manufacturers. Perusahaan farmasi asal AS itu melarang Indian Vaccine Manufacturers memproduksi vaksin PCV-13 secara generik karena persoalan paten.
"Akhirnya India dilarang mengembangkan vaksin itu sampai 2026. Pemegang paten akan memiliki hak untuk memblokir adanya transfer knowledge, memblokir manufaktur lain untuk mengembangkan vaksin dan obat generik, dan bisa mengendalikan harganya dan royaltinya," jelas dia.
Demi meredam meluasnya penyebaran Sars-Cov-2 secara signifikan, Citta berharap WTO mengabulkan proposal TRIPS waiver yang diajukan India cs. Menurut dia, pandemi Covid-19 sulit untuk diatasi jika akses terhadap produk-produk medis tetap terbatas seperti sekarang.
"Pandemi tidak akan berakhir sampai vaksinnya merata di seluruh dunia dan sekarang (negara-negara berpendapatan rendah) memang cukup dirugikan. Vaksin Moderna, misalnya, sudah dinegosiasikan semuanya untuk negara maju. Vaksin Pfizer mayoritas juga untuk negara-negara maju," terang dia.
Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra setuju hak properti intelektual dalam TRIPS diabaikan sementara hingga pandemi usai. Pasalnya, vaksin dan obatan-obatan untuk mengatasi Covid-19 dibutuhkan bukan untuk kepentingan komersialisasi.
"Dalam keadaan normal, vaksinasi atau temuan bibit vaksin secara alamiah tidak masalah. Semua lembaga berhak untuk melakukan inisiasi hak paten atas temuan itu. Akan tetapi, ketika menyangkut emergency pandemi global, ini bukan kepentingan bisnis semata," ujarnya kepada Alinea.id, Rabu (13/1).
Hermawan mengatakan pengabaian regulasi-regulasi tertentu merupakan hal yang wajar dalam penanganan pandemi. Ia mencontohkan dikeluarkannya izin penggunaan darurat (emergency use authorization) vaksin Sinovac oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).
"Itu bukan hak edar, tapi izin penggunaan dalam keadaan darurat kesehatan. Jadi, karena sifatnya izin, maka pengecualian. Ini kaitannya dengan pandemi karena ada Keppres Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatakan kondisi kita saat ini kondisi kedaruratan masyarakat," kata dia.

Komersialisasi sulit dihindari
Mantan Kepala BPOM Sampurno mengatakan komersialisasi vaksin Covid-19 sulit dihindari. Pasalnya, perusahaan farmasi telah mengeluarkan modal yang sangat besar untuk mengembangkan vaksin. Tanpa paten dan royalti, perusahaan dipastikan merugi.
"Agak sulit pelepasan (paten) vaksin dalam kondisi emergency sebab kebutuhan vaksin ini jauh lebih besar ketimbang kapasitas memproduksi vaksin pada tingkat dunia. Akhirnya, jadi rumit urusan hak paten dan hak kesehatan masyarakat ini," ujar Sampurno kepada Alinea.id, Kamis (14/1).
Dalam skema hak paten, kata Sampurno, ada tiga hal yang bisa dikenai royalti, yakni formula vaksin, teknologi pembuatan, dan hasil akhir produk vaksin. Ketiga hal itu yang membedakan vaksin bikinan satu perusahaan dengan perusahaan lain dan menjadi daya tarik vaksin yang mereka bikin.
"Apakah mereka akan ngasih cuma-cuma kepada negara yang bersangkutan? Itu (vaksin) adalah bisnis. Misalnya teknologi yang digunakan Pfizer dan teknologi yang digunakan Sinovac kan beda. Itu riset mereka memang. Tapi, tiba-tiba dengan alasan kemanusiaan kemudian India meminta, enggak bisa," tutur dia.
Meskipun atas nama kemanusiaan, Sampurno berpendapat, perusahaan-perusahaan farmasi bakal sulit merelakan formula atau teknologi vaksin mereka disebarluaskan secara gratis. Di sisi lain, paten juga dibutuhkan sebagai jaminan keamanan produk.
"Di situ ada tanggung jawab, apakah produknya itu safety dan terjamin. Apakah ada jaminan kualitasnya atau keamanannya bisa sebaik yang dibuat Sinovac oleh Pfizer bila dibuat (perusahaan farmasi lokal) di negara lain," ucap Sampurno.

Menurut Sampurno, produksi vaksin tanpa paten yang jelas justru berbahaya. Jika vaksin menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, publik yang dirugikan justru bakal kesulitan menuntut perusahaan farmasi untuk bertanggung jawab.
"Kalau terjadi kasus, tidak bisa dituntut secara hukum. Apa ada jaminan, misalnya, Pfizer (diperbolehkan) melepas ke Afrika Selatan? Apa ada jaminan bahwa yang diproduksi Afrika Selatan itu aman? Kalau terjadi apa-apa, siapa yang dituntut? Enggak segampang itu untuk melepaskan," ucap Sampurno.
Lantas bagaimana untuk keluar dari dilema paten vaksin? Sampurno menyarankan dua cara. Pertama, negara mendanai perusahaan atau lembaga riset untuk membuat vaksin secara mandiri.
"Meski perlu waktu yang cukup lama antara dua sampai tiga tahun, seperti vaksin Merah Putih," ujar dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila itu.
Kedua, pemerintah membeli formula untuk vaksin dikembangkan secara mandiri di dalam negeri, seperti halnya kerja sama antara Sinovac dan PT Bio Farma (Persero).
"Tahap pertama China ekspor ke Indonesia. Selanjutnya Sinovac memberikan bahannya ke Bio Farma, kemudian diolah oleh Bio Farma. Cara ini tergantung negosiasi kedua negara," ujar dia.