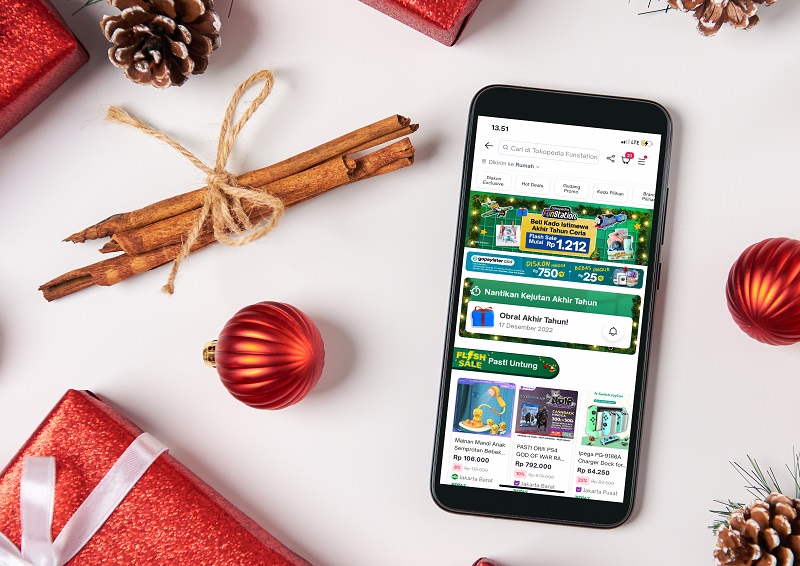Agar Natal tak berakhir jadi ritual tradisional
Akhir pekan lalu dirasa berbeda buat Christina. Mestinya, Sabtu (23/12) ada kewajiban masuk kantor hingga tengah hari, namun ia memilih cuti. Sedari pagi, ia sibuk mengemas ranselnya dan bergegas pergi ke Bandara Soekarno Hatta beberapa jam berselang. “Setahun enggak pulang. Natal jadi kesempatan buat bertemu keluarga dan beribadah di gereja bersama,” ujarnya pada saya.
Christina adalah karyawan salah satu perusahaan pembiayaan di Jakarta Selatan. Dengan jam kerja padat dari Senin sampai Sabtu, jarang sekali perempuan 30 tahun itu bisa pulang ke Kupang, NTT, tempat asalnya. Sehingga, momentum Natal sendiri ia maknai sebagai perayaan religius yang pantang buat dilewatkan.
“Sebagai perantau, jika dengar kata Natal seperti dengar kata rumah. Natal memberi kesempatan untuk pulang, sejauh apapun berkelana. Sama seperti Natal yang dimaknai sebagai waktu ‘pulang’ ke Tuhan. Maksudnya, menjadi manusia yang lebih baik lagi,” terangnya.
Senada, Daniel Gotfried Sianturi juga memaknai Natal sebagai momentum pas untuk beribadah ke gereja bersama keluarga besar. “Natal adalah peringatan atas hari kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Sebagai perayaan religius, wajar jika umat Nasrani bersuka cita,” ungkapnya, kemarin.
Lantaran merasa suka cita dirasakan hingga beberapa hari pasca-peringatan kelahiran Tuhan, ia berharap bisa mengambil jatah libur tambahan dari kantornya. “Kampung saya jauh di Medan sana. Kalau hanya diberi libur dua hari, hanya lelah di jalan,” tukas alumni Universitas Telkom Bandung tersebut.
Jika Daniel berharap bisa pulang demi menghayati suka cita Natal, Nadya Yolanda memilih untuk tetap tinggal di Jakarta. “Bagi saya di mana saja memperingati Natal, tak jadi soal, meskipun itu berarti saya tak pulang kampung ke Yogyakarta,” tutur karyawan bank plat merah tersebut.
Natal tahun ini, akan diisinya dengan rentetan kegiatan, mulai latihan intensif paduan suara gereja hingga ziarah ke makam keluarga di Jakarta. Lalu seperti Natal yang sudah-sudah, ia hanya akan berdoa dan banyak merenungkan hidup selama setahun belakangan.
Sejarah Natal, sejarah pembebasan
Seperti jamaknya umat Nasrani di Indonesia, Natal biasanya sebatas dimaknai sebagai perayaan religius yang tradisional. Mereka akan pergi ke gereja, berdoa, dan melakukan berbagai ritual khas Natal termasuk gelar griya atau pergi ke panti asuhan. “Beda dengan Barat yang mana Natal dipandang sebagai hari raya semua orang, tak peduli agama mereka. Di indonesia, Natal hanya dihayati dalam koridor Nasrani. Masih tradisional bahkan cenderung sarat ritual yang kosong,” terang Pendeta Gereja Komunitas Anugerah Salemba, Suarbudaya Rahadian pada saya.
Padahal, menurut pria yang juga aktif sebagai pengasuh rubrik Kristen Progresif Indoprogress ini, Natal punya sejarah panjang yang sayang jika hanya disederhanakan sebagai peringatan seremonial.
Dalam tulisannya “Natal dan harapan tentang dunia baru” (2018) di Indoprogress, ia mengisahkan, Natal tak bisa dilepaskan dari ide tentang pembebasan. Palestina yang kala itu menjadi ladang subur pertarungan kepentingan berbagai pihak, membuat publik rentan putus asa. Agar umat Nasrani tak patah arang, imaji para nabi soal mesias, yang mampu melepas bangsa dari jerat imperialis, terus dihidupkan, mulai dari kitab kejadian sampai Yesaya.

Saat imaji itu gagal direalisasikan, berita kelahiran Yesus dengan segera membuat girang kelompok buruh upahan di sana. Sejarah Natal, lepas dari keyakinan soal waktu kelahiran pada 25 Desember di tahun Masehi, dengan kata lain adalah sejarah optimisme. “Peristiwa Natal sejak awal hadir untuk kelompok pekerja paling rentan. Itu memberi inspirasi di mana-mana agar orang enggak menyerah pada nasib, sebagaimana Tuhan mengutus firmannya untuk mengintervensi dunia,” terangnya pada saya, Minggu (23/12).
Maka tak heran, imbuhnya, jika Natal pernah dilarang di Imperium Romawi. Pasalnya, semangat Natal berbau “makar”, sehingga dikhawatirkan mampu menggoyang stabilitas rezim.
Lantaran sejarahnya itulah, Natal mestinya dimanfaatkan untuk mengintervensi sistem yang zalim. “Sayang di Indonesia, semangat ini belum sampai sana. Jadi, masih sebatas romantisme saja,” bebernya.
Di Amerika Serikat, Natal tak lagi dipandang sebagai perayaan religius. Menurut penelitian Pew Research Centre dari wawancara 1.503 orang pada 2017, 46% di antaranya merayakan Natal sebagai hari libur keagamaan, dan 9% menilai sebagai hari raya agama dan budaya. Mengutip New York Times, sejak Trump menjabat Amerika-1, mengucapkan “Selamat Natal” mengalami pergeseran seperti mengucapkan “Selamat liburan”.
Suarbudaya sendiri menjelaskan kejadian Christmast War di Paman Sam sebagai isu primordial belaka. Kaum fundamentalis Republikan menurutnya memang kerap memakai isu bahaya sekularisasi sebagai jualan politik dan isu pengikat. Namun, di balik itu semua, ada efek yang relatif terasa, Natal tak dianggap seremonial lagi.
Untuk prekariat
Masalahnya, yang terjadi di Indonesia hari-hari ini, imbuh Suarbudaya, membutuhkan pemaknaan baru yang lebih berani dibanding kasus di Amerika. “Natal harus dipandang sebagai hari raya keagamaan yang memberi bahan bakar untuk mengritik kekuasaan yang menindas. Ini bukan cuma di ranah politik elektoral saja, tapi dalam bidang relasi kuasa dalam bahasa, kebudayaan, dan lainnya,” tuturnya.

Konkretnya, tambah ia, Natal menjadi pengingat agar kita tak mudah terima narasi-narasi politik di media arus utama, seperti Cebong versus Kampret misalnya. Di bidang budaya, ia mengajak umat Nasrani kritis terhadap kearifan lokal. “Contoh isu pemotongan salib di Kotagede, Yogyakarta kemarin yang dibiarkan dengan dalih kearifan lokal,” keluhnya.
Di bidang bahasa pun demikian. Misalnya, lanjut ia, bagaimana publik merepresentasikan kelompok tertindas dengan bahasa di media. Seperti yang terjadi di Papua yang dibingkai sebagai konflik antarnegara vis a vis kelompok separatis bersenjata. Padahal, menurutnya, peta kejadian tak sesederhana itu.
“Intinya, Natal menantang kita untuk meninjau ulang semua aspek kehidupan,” jelasnya.
Khususnya bagi para kelas buruh, apalagi prekariat (karyawan kontrak dan outsourse), Natal perlu dimaknai sebagai semangat solidaritas terhadap kawan yang dirumahkan, tak memperoleh perlakuan adil dalam urusan upah, jam kerja, dan lainnya.
Seperti yang terjadi di masa lalu saat pendeta Samuel Sharpe (1804-1831) dari jamaica berhasil memimpin pemogokan massal 300.000 budak pekerja perkebunan kapas selama sepuluh hari. “Gerakan yang lebih dikenal dengan Baptist Chrismast War yang dilansir dari tulisan Suarbudaya, turut mendorong kemunculan UU Slavery Abolition Act pada 1833, yang meniadakan perbudakaan dan pekerja anak di seantero Inggris.
“Berkaca dari masa lalu, Natal selalu memberi inspirasi untuk membangun sikap kritis terhadap struktur yang mapan. Itu yang mestinya dipertahankankan semangatnya,” tandasnya.