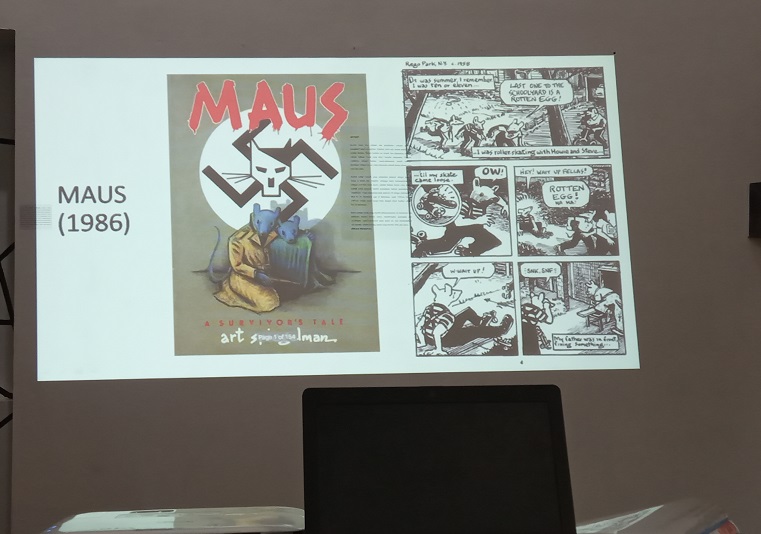Manis-getir lembaran hidup sastrawan Nh Dini
Selain Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana, La Barka karya Nh. Dini merupakan novel yang pertama kali saya baca, saat duduk di bangku SMP. Tentu saja, kita semua terkejut kala datang berita duka dari sastrawan perempuan berusia 82 tahun itu.
Selasa (4/12) sore, Nh. Dini mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol Tembalang, Semarang. Mobil yang membawa Dini dihantam sebuah truk yang meluncur mundur. Dia wafat, karena luka di kepala dan kaki kanan.
Pramugari jadi pengarang
Nh. Dini lahir di Semarang pada 29 Februari 1936. Nama asli pengarang ini adalah Nurhayati Srihardini Siti Nukatin.
Dia menekuni dunia menulis sejak 1951, saat masih duduk di bangku kelas II SMP di Semarang. Menurut Jana dalam artikelnya di majalah Varia edisi 12 Oktober 1960, sewaktu masih duduk di bangku SMA, Dini aktif dalam perkumpulan sastra. Dia pun bergiat di RRI Semarang.
“Pendengar RRI Semarang tentu tak asing lagi dengan suaranya yang merdu, saat berdeklamasi atau menjadi pemain sandiwara radio,” tulis Jana dalam Varia, 12 Oktober 1960.
Jana menulis, pada 1955 untuk kali pertama Dini menginjakkan kaki di Jakarta. Dia menjadi pramugari di Garuda Indonesia Airways. Namun, namanya sebagai seorang pengarang, sudah kadung dikenal oleh sejumlah sastrawan di Jakarta.
Tulisan pertama Dini berjudul “Pendurhaka”, dimuat di majalah Kisah. Tulisannya itu mendapat pujian sastrawan terkemuka Indonesia, HB Jassin.

Beberapa karya sastrawan Nh. Dini. (www.facebook.com/hairus.salim).
“Dini populer (di Jakarta), terutama setelah dia mengirimkan bunga selamat ulang tahun kepada HB Jassin,” tulis Jana.
Jana menulis, setelah menjadi seorang pramugari, Dini masih menulis. Tulisan-tulisannya bahkan banyak terinspirasi tentang “udara”. Menurut Jana, tulisan-tulisannya yang menyoroti tema-tema “udara” terbit di majalah Siasat dan Mimbar Indonesia.
Pada 1956, Dini menerbitkan buku kumpulan cerita pertamanya, Dua Dunia. Buku ini diterbitkan oleh NV Nusantara, Bukittinggi.
Dini menikah dengan wakil konsulat Prancis di Jakarta Yves Coffin. Pada 9 Juni 1960 keduanya menikah di Kobe, Jepang. Namun, Dini tak berhenti menulis. Tulisan-tulisannya masih bisa dinikmati pembaca Mimbar Indonesia. Pada 1960, terbit Hati jang Damai.
“Oleh kalangan sastra, Nh Dini dianggap sebagai pengarang wanita yang tajam dan teliti pengamatannya pada keadaan masyarakat, karena itu dia termasuk pengarang terkemuka,” tulis Jana dalam Varia, 12 Oktober 1960.
Hidup yang tak mudah
Dalam dunia kesusastraan, nama Nh. Dini memang tak bisa diragukan lagi. Dia sudah mempublikasi banyak karya, di antaranya La Barka (1975), Pada sebuah Kapal (1972), Namaku Hiroko (1977), Sebuah Lorong di Kotaku (1978), dan Jalan Bandungan (1989).
Dini pun menyabet sejumlah penghargaan bergengsi, seperti SEA Write Award bidang sastra dari pemerintah Thailand (2003), Hadiah Seni untuk Sastra dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989), dan Bhakti Upapradana bidang sastra dari Pemda Jawa Tengah (1991).
Seluruh prestasinya itu mungkin tak sebanding lurus dengan jalan hidupnya. Usai melanglang buana ke sejumlah negara, seperti Jepang, Filipina, Kamboja, Amerika Serikat, Belanda, dan Prancis, pada 1980 dia kembali ke tanah air.
Dini bercerai dengan suaminya pada 1984. Dari pernikahannya, Dini dikaruniai dua anak, Marie Claire Lintang dan Pierre Louis Padang.
Pada 1986, dia mendirikan sebuah taman bacaan untuk anak-anak bernama Pondok Baca di Kampung Sekayung, Semarang. Di Semarang, Dini pun hidup berpindah-pindah. Dia juga pernah tertimpa musibah bencana alam pada 1993.

Putri sastrawan Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin atau NH Dini (82), Marie Claire Lintang Coffin (kanan) berdiri di samping peti jenazah ibunya sebelum proses kremasi di Krematorium Gotong Royong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/12). (Antara Foto).
Mengutip majalah Tempo edisi 13 Februari 1993, rumah Dini di kompleks Pandana Merdeka, Semarang, diterjang banjir dan longsor. Padahal, menurut Dini, rumah sekaligus pondok bacaan anak-anak itu akan ditempati hingga akhir hayat.
“Setelah saya mati, rumah dan pondok baca itu akan saya hibahkan ke masyarakat,” katanya, seperti dikutip dari Tempo, 13 Februari 1993.
Bencana alam membuat Dini pindah tiga kali, dari Kampung Sekayu ke Pandana Merdeka, lalu kembali ke Sekayu, kemudian ke perumahan Beringin Indah di Ngalian.
Banyaknya buku yang sudah diterbitkan, ternyata tak besar pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi Dini. Dalam buku Pondok Baca Kembali ke Semarang, dia mengaku, tidak bisa mengandalkan royalti dari buku-buku karangannya sebagai nafkah hidup.
Dari penerbit, royalti yang diberikan hanya 10% dari harga jual buku. Namun, menurutnya, dia harus membayar pajak 15% dari penghasilan tersebut.
“Kuanggap ini sangat tidak adil jika dibandingkan para pelukis yang sama sekali tidak membayar pajak,” kata Dini dalam Pondok Baca Kembali ke Semarang.
Lebih lanjut, Dini mengatakan, sastra di Indonesia masih sangat spiritual, belum komersial. Menurut dia, orang-orang kagum terhadap sastrawan, seperti dirinya. Para pakar sastra di luar negeri pun tak sedikit yang menyukai buku-bukunya.
“Tapi, kekaguman itu hanya angin, tidak bisa dijadikan sarana menunjang biaya hidup si pengarang,” ujar Dini dalam buku Pondok Baca Kembali ke Semarang.
Dikremasi
Empat tahun belakangan Dini menghuni Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik. Sebelumnya, dia tinggal di Wisma Lansia Langen Wedhasis, Ungaran. Di masa-masa senjanya, dia memilih tinggal di wisma lansia, karena tak mau merepotkan orang-orang di sekitarnya.
Rabu (5/12) siang, jenazah Dini dikremasi di Ambarawa. Perihal permintaannya untuk dikremasi sebenarnya sudah ada sejak usianya 52 tahun.
Saat itu, menurut majalah Tempo edisi 20 Juli 1991, Dini mendatangi kantor notaris Lenie Hardjanto Lubis di Semarang. Dia mendaftarkan surat wasiat, yang berisi permintaan dikremasi bila sudah tiada.

“Lebih praktis dibakar, tidak membutuhkan tanah kuburan,” katanya kepada Tempo, 20 Juli 1991.
Penulis yang juga aktivis lingkungan ini beralasan, selain harga tanah kian mahal, lahan yang diperuntukkan sebagai kuburan lebih bermanfaat dijadikan tempat bercocok tanam.
Penulis dan peneliti Hairus Salim mengenang karya Dini karena deskripsi yang menarik tentang rumah tempat tinggal, anggota keluarga, dan sudut-sudut kota.
“Di sana lahir dan mengalir cerita seiring pengembaraan tokoh-tokohnya,” tulis Hairus dalam akun media sosialnya.
Sedangkan penulis muda Artie Ahmad mengenang Dini sebagai sosok yang lembut bila berbicara, namun juga tegas.
“Saya belajar dari ketegaran hidupnya. Apa yang menjadi pedoman hidupnya, benar-benar beliau pegang sampai tutup usia,” kata Artie.