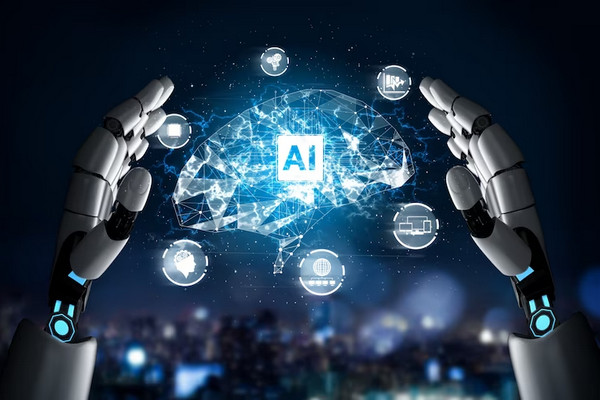Ketika AI menjadi kawan, bukan lawan
Mei lalu, Gabriela de Queiroz, Direktur AI Microsoft, beserta timnya, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasannya sederhana namun menohok: sistem yang mereka ciptakan kini mampu melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien. Microsoft, sepanjang tahun 2025 yang baru dijalani setengahnya, telah memecat lebih dari 15.000 karyawan. Kata CEO Microsoft Satya Nadella, alat seperti GitHub Copilot kini mampu menulis 30% kode baru. Ironis, bukan? Mereka yang menciptakan AI kini digantikan oleh ciptaan mereka sendiri.
Saya teringat kisah lama tentang John Henry, pengebor batu legendaris Amerika yang bertarung melawan mesin uap. Ia menang, tapi kemudian mati kelelahan. Kemenangan yang sia-sia. Apakah kita semua akan menjadi John Henry-John Henry modern, berjuang melawan algoritma hingga titik penghabisan?
Kita memang berada di ambang era baru. Seperti smartphone yang menggantikan ponsel biasa, seperti fotografi digital yang menggantikan film, AI akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan profesional kita. Tidak terhindarkan.
Tapi apakah ini berarti kiamat bagi pekerjaan manusia? Saya ragu. Sejarah mengajarkan bahwa kita selalu menemukan cara baru untuk berkontribusi, menciptakan nilai, dan menemukan makna dalam pekerjaan.
Sejarah memang berulang dengan variasi. Revolusi industri menggantikan tenaga otot, revolusi digital menggantikan tenaga administrasi, dan kini revolusi AI menggantikan tenaga pikir. Tapi setiap gelombang perubahan selalu melahirkan bentuk-bentuk pekerjaan baru yang tak terbayangkan sebelumnya.
Siapa yang membayangkan profesi "manajer komunitas media sosial" pada tahun 1990-an? Atau "spesialis optimasi mesin pencari"? Atau "pengembang aplikasi smartphone"?
Kini, di tengah badai AI, lahir pula profesi-profesi baru: "prompt engineer" yang merancang instruksi presisi untuk AI, "AI ethics consultant" yang memastikan algoritma tidak mengandung bias berbahaya, "AI-human collaboration coach" yang melatih manusia bekerja berdampingan dengan AI, atau "synthetic data curator" yang menyusun dan memverifikasi data untuk pelatihan AI.
Tapi apakah ini cukup? Apakah jumlah pekerjaan baru akan sebanding dengan yang hilang? Atau kita sedang menyaksikan awal dari era pengangguran teknologi massal?
**
Tapi tentu saja, tidak semua pekerjaan bisa digantikan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sentuhan manusia.
Seorang dokter bedah saraf, misalnya. Ia tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tapi juga intuisi yang datang dari ribuan jam pengalaman. Ia perlu membaca ekspresi wajah pasien, merasakan ketegangan otot, dan membuat keputusan dalam hitungan detik berdasarkan informasi yang tidak lengkap. AI mungkin bisa membantu mendiagnosis, tapi ia tidak bisa menggantikan kehadiran manusia yang menenangkan di saat-saat kritis.
Atau seorang guru. Ia tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menginspirasi, memotivasi, dan membentuk karakter. Ia memahami bahwa murid yang melamun di kelas mungkin lapar, atau sedang mengalami masalah di rumah, atau hanya bosan dengan metode pengajaran. AI mungkin bisa menyesuaikan materi pembelajaran, tapi ia tidak bisa memberikan pelukan yang dibutuhkan seorang anak.
Pekerjaan-pekerjaan ini aman bukan karena kompleksitasnya, tapi karena kemanusiaannya.
Seorang teman yang bekerja di perusahaan teknologi bercerita bahwa ia kini memiliki "asisten virtual" berbasis AI. Bukan sekadar chatbot sederhana, tapi entitas digital yang mampu menganalisis data, menulis laporan, bahkan menyusun presentasi. "Saya tidak lagi menghabiskan waktu untuk pekerjaan administratif," katanya. "Saya bisa fokus pada hal-hal strategis."
Perusahaan seperti Axon Enterprise menggunakan AI untuk mengurangi waktu penulisan laporan polisi hingga 82%. Ini membebaskan petugas untuk lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dentsu menggunakan AI untuk memangkas waktu analisis hingga 80%. Ini memungkinkan analis untuk fokus pada interpretasi dan strategi.
AI bukan pengganti, tapi pembebas. Ia membebaskan kita dari kerja-kerja mekanis dan memberi kita ruang untuk menjadi lebih manusiawi.
Menjadi bos yang efektif bagi AI berarti memahami bahwa ia adalah alat, bukan tujuan. Kita perlu memahami bahwa AI tidak memiliki niat, tujuan, maupun kesadaran. Ia hanya memproses pola. Ia mungkin unggul dalam menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan mengotomatisasi tugas berulang. Tapi ia buta terhadap konteks sosial yang halus, tidak memiliki intuisi, dan tidak memahami nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam.
Lebih baik delegasikan pada AI apa yang ia lakukan dengan baik: menyusun jadwal, mengorganisasi data, membuat draf awal, menganalisis tren. Tapi pertahankan apa yang membutuhkan sentuhan manusia: pengambilan keputusan etis, negosiasi kompleks, kreativitas radikal, dan empati.
**
Lalu bagaimana dengan etika? Apakah pantas publik menghargai karya cipta seseorang yang dibantu AI?
Pertanyaan ini mengandaikan bahwa ada karya yang murni hasil kreasi manusia. Tapi bukankah semua karya adalah hasil dari pengaruh, pembelajaran, dan inspirasi dari karya-karya sebelumnya? Shakespeare meminjam plot dari kisah-kisah lama. Picasso terinspirasi oleh seni Afrika. Bahkan Mozart belajar dari Haydn.
Kini kita bertanya: apakah penulis yang menggunakan AI untuk menghasilkan draf awal atau menyempurnakan tulisannya masih bisa disebut penulis? Apakah komposer yang menggunakan AI untuk mengeksplorasi melodi baru masih bisa disebut komposer?
Kreativitas tidak pernah muncul dari kekosongan. Ia selalu merupakan dialog dengan masa lalu, dengan tradisi, dengan karya-karya yang sudah ada. AI hanyalah alat baru dalam dialog ini. Alat tidak mendefinisikan seniman. Michelangelo menggunakan pahat, Da Vinci menggunakan kuas, penulis modern menggunakan pengolah kata, dan seniman kontemporer mungkin menggunakan AI. Yang penting adalah visi, intensi, dan keputusan kreatif di baliknya.
Ketika saya menulis ini, saya memang dibantu oleh AI. Ia menyarankan struktur, menawarkan formulasi alternatif, memberikan data lebih cepat. Tapi ide-ide, sudut pandang, dan keputusan akhir tentang apa yang masuk dan apa yang tidak – semua itu tetap milik saya. AI adalah kuas, bukan pelukis. Apakah ini mengurangi nilai dari tulisan ini? Apakah ini membuat tulisan ini kurang otentik?
Saya pikir tidak. Nilai tulisan ini terletak pada gagasan yang ingin disampaikan, pada sudut pandang yang ditawarkan, pada refleksi yang diundang. Yang perlu kita pertanyakan bukan apakah karya yang dibantu AI pantas dihargai, tapi apakah karya itu membawa nilai, makna, dan kebenaran. Apakah karya itu memperkaya pemahaman kita, memperluas perspektif kita, atau menyentuh kemanusiaan kita. Jika ya, maka karya itu pantas dihargai, terlepas dari alat yang digunakan untuk menciptakannya.
**
Sekarang, kita sampai pada pertanyaan terpenting. Apakah AI akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia seterusnya?
Mungkin, alih-alih bertanya apakah AI adalah ancaman, kita perlu bertanya: bagaimana AI bisa membantu kita menjadi lebih manusiawi? Bagaimana ia bisa membebaskan kita dari kerja-kerja mekanis sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk mencintai, untuk bermain, untuk merenung, untuk menjadi manusia?
Barangkali kita perlu mengubah cara kita memandang AI. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai kawan. AI tidak akan pernah bisa menggantikan kemanusiaan kita. Ia hanya bisa meniru aspek-aspek tertentu dari kemanusiaan itu. Ia bisa meniru kreativitas kita, tapi tidak bisa merasakan kegembiraan penciptaan. Ia bisa meniru kecerdasan kita, tapi tidak bisa memahami makna eksistensi.
Dan manusia adalah makhluk yang punya kemampuan untuk beradaptasi, untuk menemukan peluang di tengah disrupsi, untuk terus-menerus mendefinisikan ulang apa artinya menjadi manusia di era mesin yang semakin cerdas.
Seperti semua teknologi sebelumnya, AI adalah cermin yang memantulkan kembali harapan dan ketakutan kita. Yang kita lihat di dalamnya, pada akhirnya, adalah diri kita sendiri.
*Tulisan ini dibantu Stellar.ai