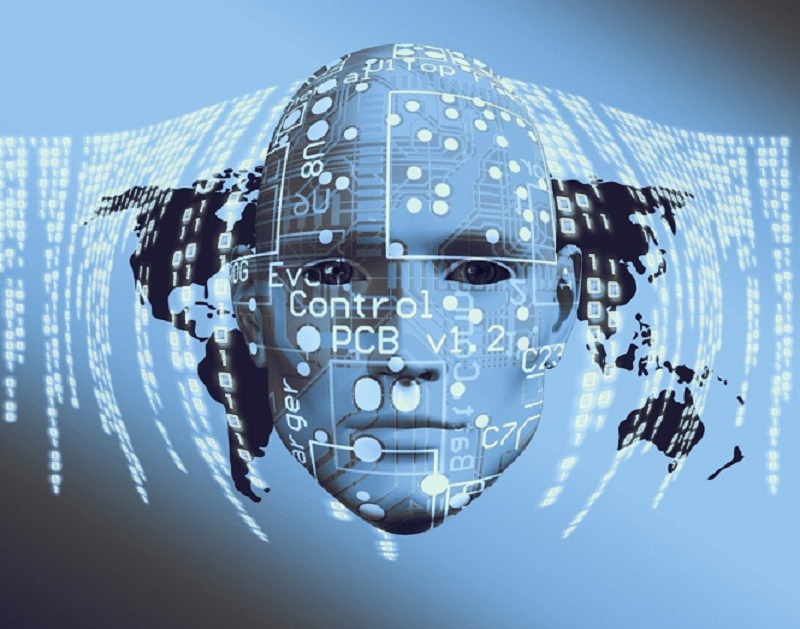Perkara hak cipta hari ini tak lagi sesederhana dulu. Ketika manusia yang mencipta, siapa yang menggugat? Tapi ketika algoritma yang menghasilkan, siapa yang pantas disebut sebagai pencipta? Buku Hak Cipta dan Artificial Intelligence karya Dr Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, dan Zahra Cintana mencoba masuk ke pusaran persoalan tersebut dengan pendekatan yang tenang namun tajam.
Kasus gugatan tiga seniman asal Amerika Serikat terhadap Midjourney, Stability AI, dan DeviantArt menjadi pemantik penting. Ketiganya menuding perusahaan teknologi itu mengambil gambar karya mereka tanpa izin, lalu menggunakannya untuk melatih sistem kecerdasan buatan. Bukan hanya tentang pelanggaran terhadap seniman, gugatan ini membuka pintu menuju perdebatan filosofis dan yuridis soal otoritas penciptaan.
Dalam pembukaannya, buku ini mengingatkan bahwa kekayaan intelektual bukan sekadar produk ekonomi. Ia adalah jejak peradaban yang menjunjung hasil olah pikir manusia sebagai sesuatu yang harus dihormati. Hak cipta, dalam konteks ini, menjadi penjaga batas antara kreasi dan komoditas. Namun kemunculan kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, gambar, bahkan musik tanpa campur tangan manusia secara langsung mengaburkan garis tersebut.
Buku ini mengajak pembaca untuk memahami prinsip penggunaan wajar atau fair use. Prinsip ini menjadi celah legal yang selama ini digunakan untuk meminjam karya tanpa izin formal dalam batas tertentu. Tapi apakah prinsip ini cukup relevan ketika entitas yang meminjam adalah mesin, bukan manusia? Pada titik ini, penulis mulai menggoyang asumsi-asumsi lama tentang relasi antara teknologi dan hukum.
Bab yang membahas ranah pendidikan menjadi titik penting. Di berbagai institusi, generative AI sudah menjadi alat bantu untuk merangkum bacaan, menyusun makalah, bahkan menciptakan ilustrasi. Ketika sebuah artikel ditulis oleh mahasiswa dengan bantuan AI, bisakah hasilnya disebut sebagai karya ilmiah otentik? Buku ini menjelaskan bahwa hukum internasional memberi ruang sejauh kontribusi manusia tetap ada dan signifikan. Kolaborasi antara manusia dan mesin bisa diakui, selama otoritas intelektual tidak sepenuhnya dialihkan kepada program otomatis.
Menariknya, penulis juga membuka cakrawala global. Tiongkok sudah memberi perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan AI, sementara Eropa menegaskan bahwa hanya karya yang diciptakan manusia yang layak mendapatkan perlindungan. Australia mulai menjajaki pengakuan terbatas, dan negara-negara seperti India, Singapura, Inggris, hingga Kanada masih mencari formula hukum yang bisa menjawab tantangan ini. Semua negara berada dalam fase eksperimentasi, menimbang antara legitimasi teknologi dan hak asasi pencipta.
Motivasi utama dari buku ini adalah memberikan kerangka pikir baru tentang hak cipta di tengah perubahan ekosistem digital. Ia tidak hanya ditujukan bagi akademisi hukum, tapi juga bagi pengambil kebijakan, pendidik, hingga praktisi teknologi yang mulai berhadapan dengan dilema etis dan yuridis dalam pekerjaan sehari-hari.
Namun buku ini juga menyisakan ruang kosong yang belum tersentuh secara menyeluruh. Perspektif industri kreatif yang telah lebih dahulu bergulat dengan AI belum tergarap secara mendalam. Pandangan para kreator konten, pengembang perangkat lunak, hingga pelaku startup teknologi seharusnya bisa memperkaya diskusi agar tidak berat sebelah. Dominasi pendekatan normatif memang penting, tapi keseimbangan dengan realitas lapangan akan membuat buku ini lebih hidup.
Meski demikian, buku ini tetap menjadi sumbangan penting bagi perbincangan hak cipta di era kecerdasan buatan. Ia tidak memberi jawaban mutlak, namun menantang kita untuk terus bertanya. Di tengah dunia yang berubah cepat, mempertahankan penghargaan atas ciptaan manusia bukan perkara sepele, terutama ketika mesin sudah mampu menulis, menggambar, bahkan mengarang puisi dengan canggih dan tanpa merasa bersalah.